Opini
Dugaan Korupsi Dana Hibah GMIM dalam Perspektif Kriminologi
Kasus dana hibah ke GMIM ini bukan sekadar persoalan hukum pidana dan moralitas individu. Konflik struktural dan kelembagaan tercermin dalam kasus ini
Oleh:
Dr Ferlansius Pangalila SH MH
Alumnus Universitas Sam Ratulangi Manado
Alumnus Program Pascasarjana Hukum dan Doktoral Kriminologi Universitas Indonesia
KEJAHATAN dalam perspektif kriminologi akan berbeda dengan hukum pidana. Sutherland, Durkheim dan beberapa kriminolog menyebut bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial (Tonkonoff, 2014) dan karenanya tidak hanya terbatas pada perbuatan yang oleh undang-undang telah dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengapa kasus korupsi dapat terjadi di lembaga keagamaan? Apa penyebab dan dampaknya? Termasuk melihat korban dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut (Sutherland & Cressy, 1960). Bagi kriminologi, hal ini bertujuan untuk memahami kejahatan dan kemudian berupaya mencegah kejahatan serupa terjadi lagi, bukan sekadar menghukum sebagaimana maksud hukum pidana.
GMIM merupakan salah satu denominasi agama Kristen Protestan dengan jumlah penganut sekitar 32 persen dari total penduduk Provinsi Sulawesi Utara. Dengan jumlah penganut yang terbilang mayoritas ini, tidak dapat dimungkiri bahwa GMIM merupakan institusi keagamaan dengan kekuatan sosial dan politik yang berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Nyiur Melambai.
Dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana hibah daerah Provinsi Sulut kepada GMIM pada tahun 2020 hingga 2023 (4 tahun) telah menyita perhatian publik. Nilai dana hibah yang diduga dikorupsi terbilang besar: Rp8.967.684.405; pejabat pemerintah dan gereja telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut yaitu 4 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan 1 orang dari Sinode GMIM (TBNews, 2025). Kasus ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya terjadi di ranah birokrasi pemerintahan atau korporasi melainkan juga merasuk institusi sosial-keagamaan yang memiliki kekuasaan simbolik dan moral yang kuat dalam masyarakat.
Dugaan kasus korupsi ini merupakan isu luar biasa, merupakan bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime), karena para tersangka adalah pejabat dengan kedudukan “terhormat” dalam masyarakat. Hal menarik karena dugaan korupsi ini terjadi dalam ruang sakral yang seharusnya bebas dari berbagai praktik penyimpangan. Korupsi memang bertentangan dengan ajaran moral, namun boleh terjadi karena desonansi etika dan mimbar telah dijadikan sebagai tempat legitimasi kekuasaan dengan praktik kuasa elite gereja.
Reaksi masyarakat dalam bentuk pro dan Kontra telah terjadi dan mengindikasikan munculnya konflik struktural. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak tertentu dengan cara menghilangkan kritik internal, memperkuat loyalitas jemaat pada pejabat hierarki yang terlibat dan cenderung mengarahkan jemaat untuk diam merupakan reaksi pro yang cenderung ke rasionalisasi. Sementara pihak lain yang kontra oleh para kritikus yang melihat bahwa dana hibah merupakan dana publik yang dapat diselewengkan melalui celah regulasi yang diduga manipulatif dan membuka praktik korupsi, dan dugaan korupsi ini menimbulkan tidak hanya kerugian negara namun juga melukai kepercayaan jemaat GMIM.
Oleh karena itu, kasus dugaan korupsi dana hibah GMIM menjadi menarik untuk dilihat dari sudut pandang kriminologi. Tujuan artikel ini adalah untuk memahami dugaan korupsi dana hibah yang melibatkan lembaga keagamaan dan pemerintah daerah. Selain itu sebagai pengantar diskusi ilmiah dan landasan penelitian kriminologi di daerah Nyiur Melambai dengan berbagai karakter sosiologis yang ada.
Perspektif Kriminologi
1. Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)
Edwin H. Sutherland (Sutherland E.H., 1983) menyampaikan bahwa ada jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat dan berstatus sosial yang tinggi serta tidak dikategorikan sebagai orang miskin. Kejahatan ini adalah kejahatan kerah putih (white collar-crime), yang berbeda dengan kejahatan kerah biru (blue collar-crime) atau penjahat-penjahat dari kalangan buruh, bergaji rendah dan berstatus sosial rendah, yang pada zaman itu umumnya menggunakan pakaian buruh dengan kerah warna biru.
Unsur terpenting dalam kejahatan kerah putih adalah: status pelaku, bahwa pelaku secara sosial dan jabatan baik dalam pemerintahan maupun organisasi sosial adalah berkedudukan tinggi. Hal ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa pelaku kejahatan ini dalam kehidupan sosial adalah orang-orang dengan status “yang terhormat”. Unsur berikutnya adalah karakter jabatan pelaku, bahwa jabatan yang sah disalahgunakan oleh pelaku, atau juga disebut sebagai penyalahgunaan peran pekerjaan (the abuse of an occupational role). (Braithwaite, 1989) (Hagan, Structural Criminology, 1988).
Pada kasus dugaan korupsi ini, para tersangka merupakan orang-orang yang memegang posisi yang lebih berpengaruh dan dipercaya oleh masyarakat. Para tersangka memiliki posisi otoritatif yang dapat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu dengan tanpa adanya pengawasan yang memadai dari masyarakat maupun pemerintah sendiri.
Lima orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulut pada tanggal 7 April 2025 yang lalu merupakan para pejabat dengan status kedudukan yang terhormat. Empat orang merupakan pejabat tinggi di Provinsi Sulawesi Utara dan satu orang tersangka merupakan pejabat tinggi lembaga geagamaan GMIM. Dilihat dari status tersangka maka unsur white collar crime telah terpenuhi. Di samping keyakinan penyidik berdasarkan alat bukti yang ada dan sah bahwa kelima orang tersangka tersebut patut diduga melakukan kejahatan korupsi dengan peran pekerjaan masing-masing (the abuse of an occupational role).
Di dalam masyarakat kelima tersangka dikenal sebagai orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang kuat. Beberapa waktu yang lalu bahkan pengacara salah satu tersangka menyatakan di depan publik dan viral melalui berbagai media sosial bahwa klien (salah satu tersangka) merupakan orang yang secara ekonomi berada (kaya). Namun mengapa dugaan kejahatan ini dapat terjadi dan dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial terutama secara ekonomi tergolong “kaya”?
Dalam beberapa kasus serupa, white collar-crime terjadi karena didorong oleh motivasi pribadi seperti keuntungan finansial, namun boleh jadi keuntungan finansial adalah faktor kedua setelah faktor keuntungan politik tertentu misalnya adanya dugaan hubungan atau kedekatan tersangka dengan pejabat politik lokal atau elite sosial lainnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan faktor keuntungan politik menjadi dorongan kuat terjadinya dugaan korupsi dana hibah tersebut (dalam beberapa kesempatan persoalan ini diperbincangkan oleh masyarakat dan penasihat hukum para tersangka).















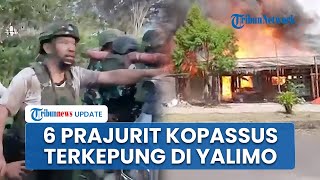





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.