Opini
Apakah Kebenaran Subjektif-Objektif Sama dengan Kebenaran Riil?
Buku ‘Penguasa Dinasti Han: Leluhur Minahasa’ terus menimbulkan pro-kontra antara budayawan-ilmuwan Minahasa.
Oleh:
Ambrosius M Loho M.Fil
Dosen Universitas Katolik De La Salle Manado
Pegiat Filsafat-Estetika
TULISAN berikut ini adalah sebuah perspektif yang bertujuan menguji sambil memberi cakrawala baru bagi pentingnya ‘posisi epistemik’ dalam sebuah penemuan-penelitian. Sejurus dengan itu, penulis justru meyakini bahwa sebuah pengetahuan baru adalah penting, termasuk pengetahuan yang didapatkan dari sebuah karya buku.
Sebagaimana umum dikenal, pengetahuan sampai menjadi pengetahuan telah melalui sebuah proses yang panjang, maka pengetahuan jugalah yang menjadikan orang atau subjek tertentu untuk mengetahui dan menguasai. Maka, terkait itu, tanpa membaca sebuah buku dengan seksama, kita tidak akan mendapat pengetahuan yang jelas dan runtut. Tanpa menyelaminya lebih dalam, tidak akan dapat menemukan sesuatu yang dicari.
Hadirnya buku ‘Penguasa Dinasti Han: Leluhur Minahasa’ (2018) yang memaparkan bahwa leluhur Minahasa itu dari Dinasti Han, dan teranyar melahirkan lagi sebuah buku berjudul ‘Pahlawan-pahlawan Dinasti Han Leluhur Minahasa’ (2024), menurut ukuran penulis, terus menimbulkan pro-kontra antara budayawan-ilmuwan Minahasa. Penulis buku sendiri bersama dengan budayawan-ilmuwan yang berada dalam kelompok yang sangat kritis menguji buku ini. Kendati demikian, pertanyaan pentingnya, entahkah kebenaran penemuan ini patut dijadikan rujukan dalam kerangka mengerti asal usul dan sumber leluhur Minahasa dan ke-Minahasa-an itu?
Kita harus mengakui bahwa dalam hal literasi, penulis buku ini sejatinya menggunakan metode falsifikasi, memfalsifikasi beberapa mitos-mitologi yang telah umum dikenal di Minahasa. (lihat Mitologi Toar Lumimuut). Kemudian, penulis menempatkan fondasional filsafat ilmu terkait penemuan-penelitian buku itu. Juga penulis memosisikan dengan rigid mitos-mitologi dan logos, yang seyogyanya tidak dimengerti dengan sebenarnya.
Dari latar itu, pertanyaan lanjutnya juga perlu dikemukakan: Apakah sebuah ilmu pengetahuan memaparkan corak riil dunia? Apakah filsafat ilmu juga memaparkan corak riil dunia, dalam artian dapat mencapai sebuah pengetahuan sejati (baca: episteme) atau kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu sudah sangat lazim di kalangan ilmuwan, secara khusus di bidang filsafat, setelah perpisahan antara filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan dengan ilmu-ilmu yang dilahirkannya, juga karena filsafat adalah aktivitas berpikir yang logis, metodis, komprehensif.
Kebenaran subjektif-objektif dalam filsafat = Kebenaran riil
Dunia filsafat adalah dunia yang mendiskusikan banyak hal, baik tentang filsafat itu sendiri maupun ilmu-ilmu yang kita kenal dan yang kita kaji secara filosofis. Tema penting yang menjadi perdebatan panjang dalam filsafat ilmu adalah apakah filsafat ilmu dapat memaparkan kebenaran sebagai corak real dunia? Kebenaran dalam filsafat ilmu bukan hanya penting pada dirinya, tapi sangat riil dihidupi oleh manusia dalam tataran praktis (individu maupun kolektif). (J. Sudarminta, Kebenaran Masihkah Bernilai: Sebuah Pengantar ke Kajian Filosofis Lintas Aliran Pemikiran, Bahan Kuliah Pasca Sarjana: STF Driyarkara Jakarta, 2014.) Namun dalam dunia kita, kebenaran selalu hanya diandaikan dan kurang dibuktikan apakah sungguh-sungguh valid atau tidak. Dari gejala ini kita menyadari bahwa kebenaran bisa diterima semata-mata hanya menurut persepsi kita/subjek. Padahal dalam filsafat ilmu, kebenaran yang sungguh-sungguh adalah kebenaran yang harus memaparkan corak riil dari ilmu sehingga bisa dikatakan ‘benar’. Dengan demikian kita harus menguji apakah kebenaran itu valid atau tidak, tentu hanya melalui diskursus dengan subjek yang lain.
Pembuktian kebenaran dalam filsafat ilmu harus dimulai dengan perbedaan ukuran kebenaran yang subjektif dan ukuran kebenaran yang objektif. Ukuran subjektif adalah ukuran berdasarkan pendapat pribadi subjek yang menilai kebenaran itu, dan ukuran objektif adalah ukuran berdasarkan cara yang dibenarkan bersama. Subjektivitas kebenaran selalu diukur berdasarkan nilai rasa subjek.
Sementara objektivitas kebenaran lebih mendalam karena mencari makna kebenaran berdasarkan argumen dan alasan secara rasional dan nalar masing-masing subjek. Membuktikan kebenaran filsafat ilmu itu benar atau tidak, harus melalui penalaran subjek yang disesuaikan dengan fakta objektif. Karena bagi filsafat, kebenaran adalah tujuan penelitian ilmiah. (Mudji Sutrisno, “Ukuran (Kebenaran),” dalam Ranah-ranah Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 15).
Bingkai pemikiran mengenai ukuran kebenaran yang riil adalah berdasarkan akal budi yang kritis rasional dan nuraninya jernih menimbang bagaimana kebenaran diukur. Bingkai tersebut berdasarkan pada: Pertama, berkembangnya peradaban kesadaran akan budi dan nurani yang semakin rendah hati untuk mengakui berlapisnya tingkatan ukuran kebenaran berdasar sudut pandang yang diukur. Dalam hal ini, bahasa menemukan perannya untuk mendefinisikan kebenaran lewat interpretasi dan penafsiran makna kebenaran. (Jose Medina and David Wood (eds.), Truth: Engangements Across Philosophical Tradition, Marlden, MA: Blackwell, 2005, p. 179.) Bingkai pertama ini merupakan pembuktian kebenaran terhadap satu hal melalui bahasa. Jadi kebenaran harus dibahasakan oleh rasio atau akal budi yang kritis. Kondisi rasio pada bingkai pertama ini menjadi penting karena kebenaran adalah apa yang akan diterima sebagai benar dan berdasarkan penemuan fakta empiris.
Kedua, berkembangnya kesadaran peradaban untuk semakin membuka ruang dalam mencari kesepakatan tentang kebenaran. Ukuran atas apa kebenaran itu merupakan hasil kesepakatan terus-menerus dalam dialog bebas dan terbuka dari masyarakat/subjek-subjek yang bersangkutan. Dalam diskursus yang terbuka dan tajam, subjek-subjek saling mengasah dari pelbagai sudut pandang, pengalaman dan persepsi, yang akan merujuk pada konsensus. Bila konsensus mengenai kebenaran dibahasakan/diinterpretasikan/ditafsirkan dengan ukuran yang adil, maka ukuran kepastian keadilan menjadi benar dan legal.
Dari sudut pandang agama, kebenaran juga diperdebatkan oleh para pemikir satu masa. Bahwa kebenaran dalam wahyu ilahi-kitab suci bergantung pada penafsiran para pembaca. Mengapa? Karena bukan tidak mungkin penafsiran pembaca bisa saja kurang rasional. Sehingga yang menjadi pokok adalah kebenaran dalam agama adalah ketika kebenaran dihidupi dan kehidupan itu dipermuliakan.
Kendati begitu, perdebatan tentang pembuktian kebenaran menjadi topik yang sangat menarik dalam filsafat ilmu. Kebenaran yang valid adalah kebenaran faktual yang teruji oleh indera. Penelusuran Galileo menunjukkan bahwa pengetahuan/kebenaran tidak bergantung pada pilihan subjek ilmuwan. Kemampuan subjek tidak menjadi ukuran mutlak pembuktian kebenaran yang sesungguhnya. Pembuktian kebenaran tidak boleh diandaikan seperti kebanyakan orang yang mengatakan bahwa kebenaran hanya sejauh itu benar. Kebenaran harus memenuhi tuntutan dan akuntabilitas dari apa yang benar itu.
Sejak zaman Yunani Kuno, kebenaran memang menjadi andaian karena dasar penentuannya adalah realitas objektif yang tergantung pada manusia. Ini berbanding terbalik dengan tesis di atas yang menekankan bukan hanya realitas subjektif tetapi juga realitas objektif. Karena itu, dalam filsafat ilmu, kebenaran adalah pertanggungjawaban yang rasional atas kepercayaan yang kita pegang dan kita terima sebagai benar. Hal ini menekankan segi rasional. Dengan kata lain, daya nalar seorang subjek sangat menentukan sebuah filsafat ilmu itu benar. Jadi pertanggungjawaban keilmuan dituntut ketika ide-ide dalam subjek mewujud dalam fakta yang membuka diri terhadap pengujian atas kebenaran ilmu itu.







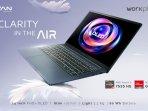













Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.