Opini
Mengembalikan Makna Pahlawan
Ketika kita memanipulasi figur pahlawan, kita juga memanipulasi identitas. Kita sedang membangun sejarah yang cacat.
Oleh:
Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd
Alumni STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado
HARI Pahlawan 2025 mengusung tema “Pahlawanku, Teladanku: Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”. Namun dalam suasana memperingati jasa para pejuang bangsa, muncul kegelisahan yang tak dapat diabaikan: generasi muda kita kian meredup dalam hal penghormatan dan keteladanan. Hubungan antara anak dan orang tua retak dalam keheningan individualisme; relasi antara murid dan guru melemah oleh budaya pragmatis dan materialistik; penghargaan terhadap sesama yang berjasa dalam hidup kian tergantikan oleh kalkulasi untung-rugi. Sementara itu, di tingkat kenegaraan, makna kepahlawanan sendiri tengah dipertaruhkan, terutama ketika gelar pahlawan menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik, sebagaimana tampak dalam kontroversi rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto – seorang tokoh yang sejarahnya dipenuhi pujian dan kecaman, pembangunan dan represi, stabilitas ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), nasionalisme dan korupsi sistemik (Aspinall & Mietzner, 2019). Di tengah serangkaian tanda tanya sejarah tersebut, kita perlu bertanya ulang: apa sebenarnya makna “pahlawan” bagi kita hari ini?
Secara filosofis, pahlawan bukanlah sosok yang sempurna, tetapi ia adalah figur yang tindakannya mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan dirinya sendiri. Aristoteles menyebut kebajikan sebagai tindakan untuk kebaikan publik yang dilakukan dengan kesadaran dan konsistensi (Shields, 2015). Dengan demikian, kepahlawanan bukan peristiwa sesaat, tetapi laku kehidupan – sebuah bentuk keberanian moral yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Namun makna ini kian tergerus dalam zaman ketika simbol lebih dihargai daripada substansi, dan prestise lebih dipuja daripada integritas. Gelar pahlawan dapat menjadi kosong ketika ia lebih ditentukan oleh kedekatan politis daripada jasa nyata bagi bangsa. Ketika gelar kepahlawanan diberikan sebagai bentuk legitimasi politik, kita bukan sedang menghormati sejarah, tetapi sedang membengkokkannya.
Dalam perspektif etika, kepahlawanan hanya bermakna sejauh ia memuliakan martabat manusia. Pahlawan adalah ia yang memampukan kita untuk melihat kehidupan sebagai ruang tanggung jawab untuk sesama. Ketika gelar diberikan kepada figur yang terlibat dalam kekerasan struktural atau korupsi sistemik, maka negara sedang mengirim pesan moral yang berbahaya kepada generasi muda: bahwa keburukan dapat dilupakan selama ada jasa tertentu, bahwa kekuasaan dapat melunasi moralitas, bahwa sejarah dapat dinegosiasikan. Pesan semacam itu merusak bukan hanya memori sejarah, tetapi juga rasa keadilan dan nurani kolektif bangsa.
Krisis keteladanan ini semakin terasa pada tingkat sosial-budaya. Masyarakat Indonesia, yang selama berabad-abad memiliki tradisi penghormatan kepada orang tua, guru, pemuka adat, dan figur moral, kini menghadapi erosi nilai yang tak kasat mata namun mendalam. Dalam arus globalisasi digital, otoritas moral tradisional tidak lagi menjadi rujukan utama. Anak muda membangun identitas melalui dunia virtual, mengikuti figur-figur yang tidak dikenal secara personal, tetapi diidolakan karena popularitas, bukan kebijaksanaan. Budaya celebrity menggantikan budaya penghormatan; ruang keluarga kehilangan otoritasnya kepada ruang layar. Kita berada dalam zaman ketika anak dapat merasa tidak berutang budi pada siapapun; ketika guru dianggap sekadar penyedia informasi, bukan penuntun kehidupan; ketika jasa seseorang dinilai bukan dari cinta dan pengorbanan, tetapi dari ukuran materi atau manfaat praktis. Inilah krisis antropologis tentang bagaimana masyarakat mentransmisikan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Pada tataran politik, persoalan kepahlawanan menjadi lebih rumit. Narasi sejarah tidak pernah netral; ia selalu ditulis oleh mereka yang memiliki kekuasaan, atau setidaknya memiliki akses pada pusat-pusat penyebar makna. James Siegel (2000) menyebut bahwa narasi sejarah Indonesia kerap disusun bukan untuk membuka kebenaran, melainkan untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan. Karena itu, gelar pahlawan nasional tidak dapat dilepaskan dari permainan wacana, ideologi, dan kuasa.
Kontroversi pemberian gelar kepada Soeharto menunjukkan bagaimana sejarah sedang dipertaruhkan dalam arena politik memori. Soeharto dipandang sebagian sebagai Bapak Pembangunan, namun dokumen-dokumen internasional menunjukkan jaringan korupsi yang begitu mengakar (Transparency International, 2004), sementara laporan HAM menunjukkan represi sistemik terhadap kebebasan sipil. Pertanyaan yang muncul bukan hanya: “Apa yang telah ia lakukan?” tetapi juga “Nilai apa yang kita ingin wariskan dengan menjadikannya pahlawan?” Jika negara mengangkat figur yang sejarahnya sarat korban, maka memoria passionis itu dipaksa untuk dilupakan. Kepahlawanan pun kehilangan bobot moralnya.
Dari sisi psikologis, generasi muda membutuhkan figur panutan yang dapat memberikan orientasi moral dan eksistensial. Erik Erikson menekankan pentingnya identifikasi pada figur yang dihormati dalam pembentukan identitas (McLeod, 2018). Tanpa figur yang dapat dihormati, anak muda mudah terjerumus dalam kekosongan identitas, sikap sinis terhadap kehidupan, dan kehilangan kompas etika. Ketika kita tidak lagi memiliki pahlawan yang jelas, kita pun kehilangan masa depan yang jelas. Pahlawan tidak hanya mengilhami tindakan, tetapi meneguhkan siapa kita sebagai bangsa.
Sementara dalam perspektif antropologis, pahlawan adalah penjaga memori kolektif bangsa. Maurice Halbwachs (1992) menegaskan bahwa identitas kolektif dibangun melalui ingatan bersama. Pahlawan adalah figur simbolik yang merawat ingatan itu agar tidak pudar. Ketika kita memanipulasi figur pahlawan, kita juga memanipulasi identitas. Kita sedang membangun sejarah yang cacat, dan generasi mendatang akan tumbuh di atas fondasi moral yang rapuh. Dengan kata lain, kontroversi mengenai sosok pahlawan bukan hanya persoalan politik, tetapi persoalan keberlangsungan watak bangsa.
Di sisi yuridis, negara sesungguhnya memiliki landasan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 menyatakan bahwa gelar pahlawan nasional hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki jasa luar biasa, keteladanan moral yang tidak tercela, dan tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Jika sejarah masih menyisakan luka, dan jika ada bukti yang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan, maka pemberian gelar tidak hanya melanggar rasa keadilan, tetapi juga prinsip hukum itu sendiri. Karena itu perlu adanya proses seleksi yang benar-benar independen, terbuka, melibatkan sejarawan, akademisi, dan publik, bukan hanya panitia birokratis yang rentan terhadap tekanan kekuasaan.
Dari seluruh refleksi ini, pertanyaan utama mengarah pada generasi muda: apa relevansi Hari Pahlawan bagi mereka yang hidup dalam realitas yang sangat berbeda dengan masa perjuangan? Relevansi itu terletak pada kesadaran bahwa kepahlawanan bukan sekadar sejarah; ia adalah tugas sehari-hari. Pahlawan bukan hanya mereka yang gugur dalam pertempuran, tetapi juga mereka yang merawat kehidupan: guru yang bertahan mendidik di pelosok, perawat yang bekerja tanpa lelah, petani yang menumbuhkan kehidupan, orang tua yang mengorbankan diri tanpa meminta balas. Namun penghormatan terhadap mereka dapat hidup hanya jika generasi muda memahami bahwa hidup manusia saling terkait dalam jaringan bakti dan terima kasih. Menghormati pahlawan berarti mengakui bahwa kita ada karena ada yang telah berjuang sebelum kita.
Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum untuk memulihkan rasa terima kasih itu. Mengembalikan penghormatan kepada orang tua bukan karena tradisi semata, tetapi karena cinta adalah fondasi kemanusiaan. Menghormati guru bukan karena kuasa simbolik, tetapi karena pengetahuan adalah jembatan hidup. Menghargai sesama yang berjasa bukan karena mereka sempurna, tetapi karena kita tidak mungkin menjadi diri kita tanpa mereka. Penghormatan bukanlah sikap feodal, melainkan kesadaran eksistensial bahwa manusia tidak pernah lahir sendirian menjadi manusia; ia dibentuk.
Pada akhirnya, Hari Pahlawan tidak hanya menuntut kita untuk mengenang, tetapi untuk memilih: nilai mana yang ingin kita tinggikan? Apakah kepahlawanan akan tetap menjadi cahaya moral bangsa, ataukah ia akan runtuh menjadi seremonial tanpa makna? Apakah generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup adalah perjuangan bersama, ataukah mereka akan tumbuh dalam budaya individualisme yang dingin dan sunyi? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan menentukan makna Hari Pahlawan, tetapi juga arah masa depan Indonesia sebagai bangsa. Jika kita tidak mampu lagi menjaga makna penghormatan dan keteladanan, maka kita sedang menuju bangsa tanpa akar, tanpa teladan, tanpa cahaya penuntun.
Namun harapan tetap terbuka. Selama masih ada yang mengingat, yang mencatat, yang membela kebenaran sejarah, yang mendidik dengan cinta, yang mengasuh dengan kesabaran, yang berjuang tanpa pamrih, pahlawan tidak pernah benar-benar pergi. Pahlawan tidak hanya hidup dalam buku pelajaran atau monumen batu; mereka hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Dan selama kita masih memilih untuk terus bergerak melanjutkan perjuangan, sebagaimana tema Hari Pahlawan 2025 menyerukan, maka kepahlawanan itu tetap menyala sebagai sumber cahaya moral bangsa. (*)
| Paskokat: Spirit Militansi Iman dalam Gerak Kemanusiaan |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Latsar-Paskokat-Sulawesi.jpg)
|
|---|
| Politik Hukum dari Dasar Kolam: Revitalisasi Sario dan Etika Kepemimpinan |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Vebry-Tri-Haryadi-21.jpg)
|
|---|
| William Shakespeare dan Chen Shou: Perspektif Sejarah Leluhur Minahasa Versi Weliam H Boseke |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Weliam-Boseke-dan-Stefi-Rengkuan.jpg)
|
|---|
| Kontroversi Dana Pemda Kabupaten Talaud Rp2,6 Triliun yang Mengendap di Bank |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Vebry-Tri-Haryadi-Opini.jpg)
|
|---|
| Membaca Ulang Kasus Prof Ellen Joan Kumaat, Rektor Bukan Kambing Hitam Proyek |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Praktisi-Hukum-Vebry-Tri-Haryadi-kasus-Prof-Ellen.jpg)
|
|---|

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Monumen-Pahlawan-Robert-W-Mongisidi-dan-Pierre-Tendean-difghdfhfgh.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Latsar-Paskokat-Sulawesi.jpg)






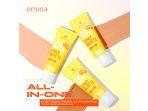


:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Monumen-Pahlawan-Robert-W-Mongisidi-dan-Pierre-Tendean-difghdfhfgh.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Vebry-Tri-Haryadi-Opini.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Dr-Drs-H-Ulyas-Taha-MPd-Kakanwil-Kemenag-Sulut-Foto.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Praktisi-Hukum-Vebry-Tri-Haryadi-kasus-Prof-Ellen.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Tulisan-opini-Rektor-IAIN-Manado-dan-Rois-Syuriah-PCNU-Manado-Foto.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.