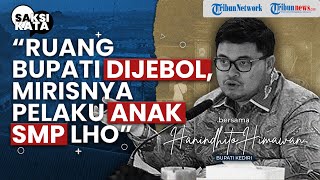Opini
Era Baru Selektivitas Orang Asing
Seiring dengan dilonggarkannya aturan pembatasan di perbatasan, makin marak pula kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan Orang Asing di Indonesia
Romel Krismanto Malensang, S.IP, MA. (Analis Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado)
Seiring dengan dilonggarkannya aturan pembatasan di perbatasan, makin marak pula kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan Orang Asing atau Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Indonesia.
Melihat ramainya pemberitaan baru-baru ini misalnya, ada kasus kejahatan pencurian data nasabah (skimming) terhadap sejumlah nasabah Bank SulutGo di Sulawesi Utara. Diperkirakan total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 3,7 miliar.
Kemudian atas laporan dari bank, pihak kepolisian menindaklanjuti dengan menetapkan serta melakukan penangkapan terhadap para tersangka di tempat berbeda pada tanggal 20 dan 21 Juli 2022.
Dari hasil penangkapan tersebut diketahui bahwa dua orang pelakunya adalah WNA asal Bulgaria berinisial MS dan VK ditangkap bersama dua orang WNI.
Baca juga: Mewaspadai Penumpang Gelap Pariwisata dan The Exercise Of Immigration Control

Sementara yang menjadi otak kejahatan ini diketahui juga adalah orang asing warga negara Bulgaria berinisial MM dan masih buron.
Untuk memburu DPO tersebut, kepolisian dibantu Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sulawesi Utara dengan memasukkan nama yang bersangkutan dalam Daftar Pencegahan agar tidak kabur ke luar negeri.
Bukan kali pertama, kasus pencurian uang dengan modus skimming ini telah sering terjadi dan menariknya rata-rata pelaku adalah orang asing.
Sebagai contoh, kasus skimming yang ditangani Polres Pasuruan pada bulan Oktober tahun 2021 melibatkan dua warga negara Bulgaria.
Bulan November terjadi kasus serupa di Bali dengan pelaku dua WNA asal Turki dan satu WNA asal Ukraina.
Bulan Mei tahun 2022, ditangani Polda Kepri dengan pelaku seorang WNA asal Bulgaria. Bulan Juni, oleh Polda Metro Jaya juga menangkap seorang WNA asal Estonia yang melakukan skimming di wilayah Cengkareng dan Kalideres, Jakarta Barat.
Itu sebagian contoh kecil saja yang bisa ditampilkan, tapi memang untuk jenis kejahatan ini sudah sering melibatkan WNA baik sebagai pelaku biasa atau selaku otak kejahatan.
Terbaru ada juga pemberitaan yang viral dimana terdapat tiga orang asing bersama rekan mereka yang merupakan WNI, diamankan Satgas Marinir Ambalat XVIII di Nunukan, Kalimantan Utara karena diduga melakukan aktivitas intelijen (spionase).
Mereka yang diduga sebagai “intel asing” itu kemudian diserahkan kepada pihak imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Maraknya perkara kriminal serta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akhir-akhir ini mengundang sejumlah pertanyaan publik.
Seperti, apa peran imigrasi? Mengapa petugas imigrasi di perbatasan justru membiarkan orang asing yang bermasalah masuk ke wilayah Indonesia?
Padahal menurut Undang-Undang, kepada imigrasi diberikan tugas untuk menjagai pintu gerbang negara. Dengan kata lain salah satu tugas utama imigrasi sebenarnya adalah memfilter siapa saja orang-orang yang “pantas” masuk atau keluar wilayah Indonesia.
Dengan adanya kasus-kasus yang ditampilkan diatas, apakah serta merta menegaskan bahwa kinerja imigrasi sedang melorot? Lantas, siapa yang harus disalahkan, perilaku petugas (human error) atau justru sistem manajemen institusinya?
Untuk merefleksikan realitas tersebut, saya mencoba menghadirkan respon dalam konteks kajian yang sederhana. Sudut pandang yang diangkat setidaknya berdasar pada suatu argumen yang meyakini bahwa kebijakan keimigrasian Indonesia harus benar-benar diletakkan pada asas selektivitas, yakni bahwa negara memiliki kewenangan absolut untuk mengatur terhadap orang-orang tertentu saja yang boleh bermigrasi ke populasi Indonesia.
Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kebijakan keimigrasian tersebut berkorelasi terhadap kecanggihan dan mekanisme negara di era baru yang sangat disruptif ini.
Diskursus Politik Hukum Keimigrasian Indonesia
Politik hukum keimigrasian di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. M. Alvi Syahrin (2019) membaginya dalam empat periode yaitu, pada masa Hindia Belanda (1913-1949), pada masa kemerdekaan (1950-1992), pada masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, terakhir saat ini masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Dari pembabakan garis sejarah tersebut, garis pokok perubahan arah kebijakan keimigrasian terjadi secara drastis mulai dari Kebijakan Keimigrasian yang bersifat Open Door Policy pada masa pemerintah kolonial, di mana orang dengan mudah dapat melintas masuk keluar wilayah negara. Akibatnya semakin banyak orang asing yang datang, bekerja, dan bermukim bahkan tanpa prosedur keimigrasian yang legal.
Memasuki era kemerdakaan hingga saat ini, terjadi peralihan yang cukup signifikan. Kebijakan keimigrasian yang awalnya bersifat terbuka menjadi politik hukum yang lebih berdasarkan kepentingan nasional dan bersifat selektif. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Kebijakan Selektif (selective policy).
Pada bagian penjelasan atas Undang-Undang 6 Tahun 2011 dijelaskan bahwa berdasarkan kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.
Meski demikian, arah politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif ini masih dianggap bermasalah pada tataran implementasi. Meski secara de jure disyaratkan selektif dalam hal lalu lintas orang asing, namun secara de facto Indonesia “masih bernuansa terbuka” dalam sejumlah kebijakan turunannya.
Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) misalnya, sejak tahun 1983 terus mengalami penambahan secara progresif jumlah negara yang warga negaranya dapat dengan bebas masuk tanpa harus memiliki visa. Puncaknya saat terbit Perpres Nomor 21 Tahun 2016 dimana jumlah negara subjek BVK mencapai 169 negara. Beruntung dengan adanya pandemi Covid-19, kebijakan ini untuk sementara dicabut terutama dalam rangka pengendalian penyebaran virus.
Memang pemerintah dalam membuat kebijakan ini semata-mata untuk memajukan sektor pariwisata. Rasionalitasnya adalah jika negara semakin terbuka, maka semakin banyak pula wisatawan asing yang akan datang.
Namun seiring dengan masifnya kedatangan orang asing pasti berimplikasi pada resiko-resiko yang dikuatirkan terjadi serta menganggu keamanan dan ketertiban dalam negeri. Apalagi berdasarkan sejumlah studi, tidak sedikit WNA yang terjerat kasus pidana keimigrasian maupun pidana lainnya masuk ke Indonesia menggunakan skema bebas visa.
Oleh karena itu menurut hemat saya, di momen pandemi sekarang perlu ada evaluasi yang serius terhadap kebijakan BVK ini agar sesuai dengan politik hukum keimigrasian kita yang berasaskan selective policy.
Negara perlu membangun kerangka aturan yang semakin memperkuat fungsi kontrol imigrasi. Pemberian bebas visa berarti meminimalkan fungsi kontrol imigrasi terhadap orang asing yang akan datang ke Indonesia dimana tahapan pemberian visa ditiadakan.
Padahal pada tahapan inilah fungsi pengawasan keimigrasian dijalankan dan menjadi Tindakan preventif untuk menjauhkan orang asing yang bermasalah atau diduga bermasalah dari wilayah Indonesia. Seleksi dan filterisasi benar-benar dilakukan bahkan sebelum orang itu tiba di entry point perbatasan Indonesia.
Sehingga hanya orang asing yang berguna dan bermanfaat bagi kita yang tiba dan masuk kedalam wilayah negara.
Perbatasan Pintar : Era Baru Kebijakan Selektif Imigrasi
Disrupsi dalam disrupsi, kira-kira adalah istilah yang dapat menggambarkan peradaban dunia saat ini. Memasuki fase 4.0 dalam revolusi industri disusul dengan mewabahnya Covid-19 menjadi pandemi global, memaksa berbagai sektor untuk selalu berinovasi dalam bentuk terbaru yang lebih efisien, efektif dan akurat.
Biasanya termanifestasi dalam bentuk penggunaan teknologi yang memadukan unsur otomatisasi dan siber yang mengurangi sekat-sekat fisik, digital dan biologi. Dalam konteks perbatasan negara, konsep Perbatasan Pintar (Smart Border) muncul sebagai respon terhadap meningkatnya gangguan dan ancaman keamanan negara di era disrupsi. Ciri khas dari perbatasan pintar adalah kontrol imigrasi yang bersifat otomatis dengan penggunaan teknologi atau minim campur tangan manusia. Disaat bersamaan juga bersifat preventif atau pemberlakuan kontrol imigrasi yang dilakukan jauh dari wilayah perbatasan teritorial.
Salah satu peristiwa yang memicu lahirnya konsep perbatasan pintar yaitu saat terjadinya tragedi 9/11 atau penyerangan di gedung World Trade Center (WTC) tanggal 11 September 2001.
Tragedi itu membuat Pemerintah Amerika Serikat mereformasi sistem keamanan perbatasan mereka. Para ahli dan pakar berkumpul untuk menemukan apa saja kebocoran-kebocoran yang terjadi di perbatasan mereka sehingga para teroris pelaku penyerangan tersebut dapat lolos dan melakukan pengeboman serta apa strategi yang dapat dilakukan sehingga peristiwa yang sama tidak terjadi lagi di masa depan.
Maka dimulailah era perbatasan pintar yang juga mulai diimplementasikan di negara-negara Eropa untuk menyeleksi para migran beresiko tinggi yang akan memasuki wilayah mereka.
Dalam sebuah Webinar Center for Migration and Border Studies (CMBS), Gusti Galuh R. Sari, M.A sebagai salah satu narasumber memaparkan secara konseptual tujuan perbatasan pintar, yaitu dapat menjalankan manajemen resiko di perbatasan.
Karena dalam konteks perbatasan, manajemen resiko adalah suatu keniscayaan. Resiko yang berimplikasi negatif mungkin kecil tapi memiliki konsekuensi yang sangat besar.
Tidak membutuhkan banyak orang misalnya untuk melancarkan kegiatan terorisme, namun dampak yang dihasilkan bisa memakan banyak korban. Begitupun dengan tindak kejahatan lainnya yang beresiko terjadi atas hadirnya orang asing.
Sebaliknya, bagi orang asing yang datang membawa keuntungan bagi negara seperti investor, wisatawan mancanegara, pebisnis, dan lain-lain semestinya mendapat fasilitas percepatan di perbatasan yang efisien.
Oleh karenanya, perbatasan pintar hadir untuk memfasilitasi kedatangan orang asing yang memiliki resiko rendah namun menjadi penghambat bagi yang memiliki resiko tinggi.
Bagaimana mengimplementasikannya? Menurut Sari, langkah pertama adalah melakukan penilaian resiko (risk assessment/risk profiling) dengan penggunaan teknologi biometric dan data analytic.
Disini diperlukan silang sumber atau integrasi database antar lembaga bahkan antar negara yang memerlukan landasan hukum dan kerjasama internasional.
Proses penilaian resiko bukan hanya dilakukan berdasarkan data pribadi yang bersifat umum saja namun menjangkau pengecekan latar belakang serta rekam jejak per individu.
Dengan menghubungkan berbagai database dan menggunakan teknologi data analytic dan algoritma secara otomatis dapat menemukan orang asing yang memiliki resiko tertentu atau berperilaku tidak wajar.
Langkah kedua, orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia dikelompokan secara sosial (social sorting) dan dibagi dalam tiga kelompok besar: hijau (aman), abu-abu (perlu pengecekan lanjutan), hitam (bermasalah).
Langkah ketiga, diberikan perlakuan yang berbeda-beda kepada orang asing yang akan masuk berdasarkan tingkat resiko yang sudah dikelompokkan diatas. Kepada kelompok hijau dipermudah, abu-abu dihambat, hitam dihentikan atau ditolak (blacklist).
Pada tahapan ini terminologi “pintar” konsep ini di produksi yaitu bahwa sistem dapat langsung memberi keputusan terhadap pengelompokkan individu termasuk perlakuan yang berbeda-beda kepada masing-masing kelompok tersebut.
Dengan menjalankan strategi perbatasan pintar harapannya asas selektivitas dalam politik hukum keimigrasian kita dapat tercapai secara lebih optimal.
Dengan teknologi, perbatasan negara dihadirkan secara virtual langsung ke hadapan orang asing yang ingin masuk, jauh sebelum orang tersebut menginjak wilayah teritorial perbatasan kita. Sehingga potensi masalah dan resiko yang melekat pada diri seseorang tersebut akan dapat dikendalikan lebih awal.
Penutup
Akhirnya saya juga harus menyatakan bahwa apapun mekanisme teknologi yang dijalankan sangat bergantung pada kualitas sumber daya petugas imigrasi itu sendiri.
Sebab meskipun penerapan perbatasan pintar mensyaratkan otomatisasi teknologi, namun peran manusia harus ada dan hadir sebagai second layer pengambilan keputusan. Terutama menghadapi anomali-anomali sistem yang mungkin saja hadir atau “dihadirkan” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga keberhasilan penerapan perbatasan pintar menjadi paripurna bila petugas imigrasi di perbatasan dilengkapi dengan kompetensi dan dimensi nilai (etika publik) yang mumpuni. (*)