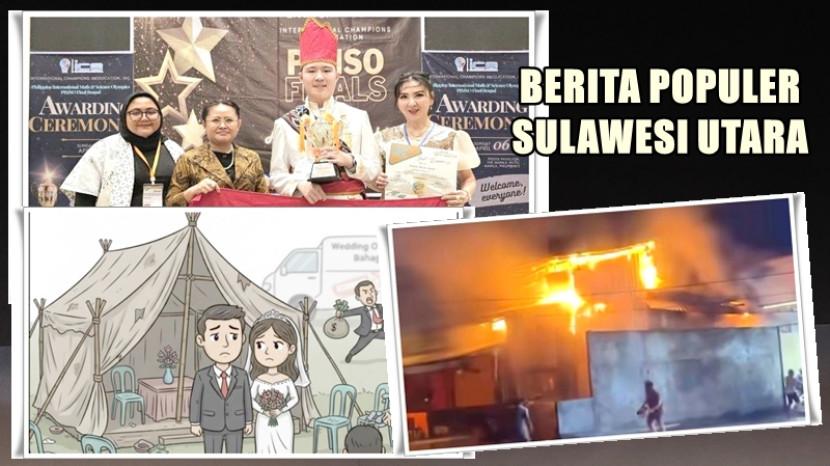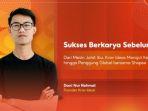Tokoh Manado
Pahlawan Nasional asal Manado, Ada Dijuluki 'Hantu Laut' Ditakuti Belanda hingga Gugur Usia 24 Tahun
Ada 9 Pahlawan Nasional asal Manado yang ditetapkan pemerintah Indonesia hingga 2019.
Penulis: Aldi Ponge | Editor: Aldi Ponge
Sebenarnya, banyak tokoh Sulawesi Utara yang menjadi pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Namun, belum semuanya diusulkan dan diterima menjadi Pahlawan Nasional.
Tokoh-tokoh kawanua tersebut menjadi sosok penting bagi kemerdekaan Indonesia.
Ada yang sudah ditetapkan pemerintah menjadi pahlawan Nasional tapi masih banyak yang belum.
Berikut daftar pahlawan nasional asal Manado yang sudah ditetapkan pemerintah:
1. John Lie - Hantu Laut
John Lie merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari etnis Tionghoa.
John Lie lahir di Manado pada 9 Maret 1911 dan wafat pada 27 Agustus 1988 pada umur 77 tahun.
Pria dengan nama lengkap Jahja Daniel Dharma ini adalah penyelundup senjata ulung untuk pejuang Ibu Pertiwi.
Saking pandainya berdalih dari armada laut Belanda yang berpatroli di laut Indonesia, John Lie sampai mendapatkan julukan sebagai 'Hantu Selat Malaka'.
John Lie bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pada tahun 1946 setelah dirinya bersama dengan puluhan rekannya di pelayaran KPM (Koninlijk Paketvaart Maatschapij) kembali ke Tanah Air pasca kekalahan Jepang pada Agustus 1945.
Sebelum bergabung dengan ALRI, rupanya John Lie mempelajari sistem pembersihan ranjau laut dari Royal Navy milik Belanda di Pelabuhan Singapura.
John Lie juga mempelajari dengan baik gerak-gerik pergerakan armada laut Belanda yang berpatroli di laut Indonesia.
Berbekal dengan pengetahuannya dan pengalamannya di dunia maritim, John Lie pun menemui Kepala Staf Angkatan Laut RI (ALRI) Laksamana M Pardi.
John Lie mengungkapkan keinginannya berjuang dengan Indonesia di bidang maritim melawan Belanda, merebut kemerdekaan.
Melansir Tribunnews, setelah bergabung dengan ALRI, John Lie pun ditugaskan untuk menjadi penyelundup barang ekspor guna membiayai kas negara.
Tak hanya barang ekspor, John Lie juga ditugaskan oleh Kepala Urusan Pertahanan di Luar Negeri untuk membeli sejumlah kapal cepat dan senjata untuk bangsa Indonesia.
Mereka menyaring dan menyusun personalia pelaut untuk mengawaki satuan kapal cepat yang digunakan memasok kebutuhan perlengkapan perjuangan Indonesia.
Sebagai salah satu pelaut yang lolos seleksi, John Lie dipercaya memimpin psebuah kapal cepat bernama The Outlaw.
Pada operasi perdananya, The Outlaw berlayar dengan rute Singapura-Labuan Bilik dan Port Swettenham.
Dikutip dari Wikipedia via Tribunnews, John Lie telah melakukan operasi penyelundupan setidaknya 15 kali.
Bahkan, ia pernah ditangkap oleh Perwira Inggris saat kapalnya membawa 18 drum minyak kelapa sawit.
John Lie juga pernah mengalami peristiwa menegangkan saat membawa senjata semiotomatis dari Johor ke Sumatera.
Saat itu, ia dihadang oleh pesawat terbang patroli Belanda. Dua penembak jitu mengarahkan senjata ke kapal mereka.
John Lie yang tak gentar pun menolak mundur saat dihadang komandan armada laut Belanda.
Setelah beberapa saat terlibat adu debat yang alot, Komanda armada Belanda akhirnya tak mengeluarkan perintah untuk menembak.
Pesawat itu malah meninggalkan The Outlaw tanpa insiden.
Belakangan diketahui ternyata pesawat Belanda tersebut pergi karena bahan bakarnya semakin menipis.
Keberhasilan The Outlaw menyelundupkan senjata ke Indonesia atau hasil bumi ke Singapura hingga Thailand terus terjadi pada misi-misi selanjutnya.
Bahkan, siaran stasiun radio BBC di London sampai menjuluki kapal tersebut dengan nama The Black Speedboat.
Kepala Subdinas Sejarah Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kolonel Syarif Thoyib mengatakan jika John Lie memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di Pelabuhan Singapura, Thailand bahkan Afrika.
Atas keberhasilannya mengelabui dan kabur dari intaian para pasukan Belanda, John Lie pun dijuluki sebagai si 'Hantu Selat Malaka'.
John Lie wafat pada 27 Agustus 1988 dan baru mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2009 di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
John Lie dianugerahkan gelar Bintang Mahaputera Adipradana dan namanya digunakan sebagai nama Kapal Perang Indonesia, KRI John Lie pada tahun 2017.
2. Alexander Andries Maramis - Pendiri Bangsa dan Suara Kaum Minoritas
Alexander Andries Maramis, atau AA Maramis, adalah tokoh penting di masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Ia termasuk tokoh yang merumuskan dasar negara Republik Indonesia bersama dalam Panitia Sembilan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945.
AA Maramis lahir pada 20 Juni 1897 di Desa Paniki Bawah.
AA Maramis masih punya pertalian darah dengan pahlawan Sulut lainnya yaitu Maria Walanda Maramis.
Ia menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1911 di sekolah elit Belanda di Manado, yakni Europeesche Lagere School (ELS).
Sekolah tersebut terletak di pusat Kota Manado, yang sekarang menjadi SD N 4 Manado.
Selesai menamatkan pendidikan dasarnya, keluarga berembuk untuk menyekolahkan AA Maramis ke pendidikan sekolah yang lebih tinggi di Batavia yakni Hogere Burger School (HBS) , mengingat saat itu Manado hanya salah satu wilayah keresidenen Ternate.
Pada tahun 1918 keluarga lalu mengirim AA Maramis ke HBS di Jalan Matraman.
Sejak bersekolah di Batavia, Maramis bertemua dengan teman-teman sebangsanya dari daerah berbeda. Di antanya Achmad Soebardjo beretnis Jawa dan Datuk Natsir Pamuntjak dari Sumatera.
Ketiganya sahabat karib ini studi di Universitas Leiden, Belanda. Ketiganya mendapat beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda selama enam tahun.
Semasa kuliah AA Maramis bertemu pemuda dari seluruh Indonesia yang kuliah di kampus yang sama. Pertemuan itu mengubah pandangan politiknya.
Dari pengamatannya ada kelompok pemuda Islam yang dipengaruhi organisasi Sarekat Islam yang di Indonesia berkembang menjadi kekuatan anti kolonial.
Begitu pula pemuda beraliran sosialis yang telah mendapat pendidikan Marxisme Leninisme mereka berafiliasi dengan sarekat pekerja untuk memerangi imperialisme.
Pada Juni 1924 AA Maramis berhasil menyelesaikan studi dan mendapat gelar Meester in de Rechten atau ahli hukum. Zaman itu tak banyak orang yang mendapat gelar tersebut. AA Maramis kembali ke tanah air pada Juli 1924.
Ia mendapat tawaran pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi pegawai mereka, namun AA Maramis menolaknya.
AA Maramis memilih menjadi pengacara bagi rakyat Indonesia yang kurang mampu. Dari sinilah perjuangan AA Maramis bagi bangsa dan negara dimulai.
Diangkat sebagai Menteri Keuangan
Dikutip dari wikipedia, Maramis diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Indonesia pertama pada tanggal 26 September 1945.
Maramis menggantikan Samsi Sastrawidagda yang pada awalnya diberi jabatan tersebut pada waktu kabinet dibentuk pada tanggal 2 September 1945. Sastrawidagda mengundurkan diri setelah hanya menjabat selama dua minggu karena sakitnya.
Sebagai Menteri Keuangan, Maramis berperan penting dalam pengembangan dan pencetakan uang kertas Indonesia pertama atau Oeang Republik Indonesia (ORI).
Dibutuhkan waktu satu tahun sebelum uang kertas ini bisa dikeluarkan secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946.
Nota-nota ini menggantikan uang kertas Jepang yang diedarkan oleh pemerintah Hindia Belanda (NICA).
Uang dikeluarkan untuk denominasi 1, 5, dan 10 sen, dengan ditambah ½, 1, 5, 10, dan 100 rupiah. Tanda tangan Maramis sebagai Menteri Keuangan terdapat dalam cetakan uang-uang kertas ini.
Maramis menjabat sebagai Menteri Keuangan beberapa kali lagi, secara berurutan dalam Kabinet Amir Sjarifuddin I pada tanggal 3 Juli 1947, Kabinet Amir Sjarifuddin II pada tanggal 12 November 1947, dan Kabinet Hatta I pada tanggal 29 Januari 1948.
Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda memulai Agresi Militer Belanda II pada saat pemerintahan Hatta. Soekarno, Hatta, dan pejabat pemerintahan lainnya yang berada di Yogyakarta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka.
Maramis pada saat itu sedang berada di New Delhi, India. Dia menerima kawat dari Hatta sebelum Hatta ditangkap dengan instruksi untuk membentuk pemerintahan darurat di pengasingan di India seandainya Sjafruddin Prawiranegara tidak dapat membentuk pemerintahan darurat di Sumatra.
Prawiranegara mampu membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dan Kabinet Darurat di mana Maramis diangkat sebagai Menteri Luar Negeri.
Setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan, Prawiranegara mengembalikan pemerintahan kepada Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 dan Maramis kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Diamanatkan Jabatan Presiden
AA Maramis pernah diamanatkan oleh Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat.
Hal itu diungkap Julius Pour dalam bukunya Doorstoot naar Djokja: Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer.
Dalam buku tersebut Julisu Pour menulis, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda memulai Agresi Militer Belanda II pada saat pemerintahan Hatta.
Soekarno, Hatta, dan pejabat pemerintahan lainnya yang berada di Yogyakarta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka.
Maramis pada saat itu sedang berada di New Delhi, India. Dia menerima kawat dari Hatta sebelum Hatta ditangkap dengan instruksi untuk membentuk pemerintahan darurat di pengasingan di India seandainya Sjafruddin Prawiranegara tidak dapat membentuk pemerintahan darurat di Sumatra.
Prawiranegara mampu membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dan Kabinet Darurat di mana Maramis diangkat sebagai Menteri Luar Negeri.
Setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan, Prawiranegara mengembalikan pemerintahan kepada Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 dan Maramis kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Kiprah di Dunia Internasional
Kiprah AA Maramis di dunia internasional di antaranya konferensi New Delhi 20-23 Januari 1949. Ia yang saat itu sebagai Menteri Luar Negeri memimpin delegasi dari Indonesia.
Perjuangan delegasi Indonesia di konferensi ini menjadi catatan penting bagi sejarah Indonesia. Karena menyangkut pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Hal ini yang menjadi harapan berjuta-juta rakyat Indonesia saat itu.
Anggota delegasi lainnya yakni wakil RI di Singapura, Mr Utoyo, wakil RI di India Dr Sudarsono, wakil RI di Mesir HA Rasyidi dan wakil dagang RI di Amerika Serikat Sumitro Djoyohadikusumo.
Setelah Konferensi New Delhi usai, AA Maramis langsung menuju PBB bersama Lambertus Nicodemus Palar yang ditunjuk sebagai juru bicara delegasi Indonesia di PBB bersama Sudarpo, Sudjadmiko dan Sumitro.
Sebagai juru bicara, LN Palar melaporkan secara resmi tentang pengakuan kedaulatan Indonesia dan hasil Konferensi New Delhi 1949 yang diperjuangkan AA Maramis.
Satu tahun kemudian membuahkan hasil, pada 28 September 1950 Indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat dan menjadi anggota resmi Perserikatan Bangsa-bangsa ke-60 dengan status anggota penuh.
“Saat Konferensi New Delhi itu, katanya AA Maramis berperilaku seperti naga. Saya mendengar itu saat penghargaan MURI tahun 2017 dari seorang wartawan senior yang hadir pada saat itu. Ia menyebut itu dalam Bahasa Belanda yang artinya itu."
"Penghargaan MURI ini untuk AA Maramis sebagai Menkeu pertama yang menandatangani 15 mata uang RI,” kata Lody Rudy Pandean
Setelah hampir 20 tahun tinggal di luar Indonesia, AA Maramis menyatakan keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur agar ia bisa kembali dan pada tanggal 27 Juni 1976 ia tiba di Jakarta.
Di antara para penyambut di bandara adalah teman-teman lamanya Soebardjo dan Mononutu, dan juga Rahmi Hatta (istri Mohammad Hatta).
Pada bulan Mei 1977, ia dirawat di rumah sakit setelah mengalami perdarahan. Maramis meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1977 di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Soebroto, hanya 13 bulan setelah ia kembali ke Indonesia.
Jenazahnya disemayamkan di Ruang Pancasila Departemen Luar Negeri dan dilanjutkan dengan upacara militer dan kemudian pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Setelah sekian lama, AA Maramis akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional jelang Hari Pahlawan 10 November 2019.
3. Arie Frederik Lasut
Arie Frederick Lasut adalah pahlawan Nasional asal Sulawesi Utara, seorang intelektual yang melawan penjajah dengan gagah berani dan tewas mengenaskan setelah disiksa dan ditembak dengan keji oleh tentara Belanda.
Arie Lasut memilih mati sebagai anak muda bangsa Indonesia yang mempunyai harga diri dan kehormatan daripada hidup mewah dan nyaman sebagai pengkhianat bangsa.
Arie Lasut lahir pada 6 Juli 1918 di Kapataran, Lembean Timur, Minahasa, Sulawesi Utara.
Arie Lasut adalah putera tertua dari delapan anak dari Darius Lasut dan Ingkan Supit.
Arie Lasut memulai pendidikannya pada tahun 1924 di sekolah dasar Belanda (Hollands Inlandse School), kemudian melanjutkan ke sekolah guru (Hollandse Inlandse Kweekschool).
Sekolah guru ini tidak diselesaikan tetapi pindah ke Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (Algemeene Middlebare School) bagian B (Wisen Natuurkundiege Afdeling (IPA)).
Setelah tamat, pada 1939 beliau ikut ujian masuk kursus asisten geologi pada Dienst van den Mijnbouw (selanjutnya menjadi Jawatan Tambang dan Geologi).
Arie Lasut kemudian berkarir serta melakukan penelitian tentang geologi dan pertambangan Indonesia yang kemudian makin menebalkan rasa cinta tanah air dan jiwa pejuangnya.
Kemudian bersama R Sunu Sumosusatro merupakan asisten ahli geologi Indonesia pertama.
Setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah kalah dari bala tentara kerajaan Jepang pada 8 Maret 1942, Dienst van den Mijnbouw diambil alih dan berganti nama menjadi Chisitsu Chosajo.
Pada zaman pendudukan Jepang, Arie Frederik Lasut bersama seluruh karyawan Indonesia tetap bekerja sama mendalami geologi dan pertambangan Indonesia.
Pada 11 September 1945, Arie Frederik Lasut ikut serta dalam pengambil-alihan Chisitsu Chosajo (jawatan geologis) dari Jepang yang berhasil dilakukan dengan damai, kemudian mengganti namanya menjadi "Jawatan Tambang dan Geologi, Ing Ngarso Sung Tulodo".
Tanggal 16 Maret 1946, Arie Frederik Lasut dipilih dan diserahi tugas menjadi Kepala Jawatan Tambang dan Geologi, pada saat usianya baru menginjak 28 tahun.
Kecerdasan, keuletan kerja, serta kepoloporannya membuat Arie Lasut yang masih muda mampu mengelola suatu jawatan yang saat itu merupakan salah satu yang terbesar di Asia.
Memang sangat luar biasa ketika pemuda tersebut mampu mengelola suatu lembaga ilmiah dan kekayaan bangsa dan negara Indonesia yang sangat bermanfaat yang terasa manfaatnya hingga saat ini.
Sekolah pelatihan geologis juga dibuka selama kepemimpinan Arie Frederik Lasut sebagai kepala jawatan saat itu.
Darah pejuang titisan Dotu Lolong Lasut yang mengalir dalam diri pemuda Arie Frederik Lasut bergejolak ketika hadirnya pasukan sekutu yang dibonceng tentara Belanda di Bandung.
Pemuda anak banga ini berpikir cerdas dan cepat untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Yang pertama terpikirkan adalah bagaimana menyelamatkan dokumen geologi dan tambang yang memuat kekayaan bangsa dan negara Indonesia. Ketika dokumen tersebut sedang dicari-cari dengan senjata oleh tentara Belanda.
Arie Lasut dengan gagah berani tanpa memperdulikan risiko ditembak Belanda secara sembunyi-sembunyi menyelamatkan berbagai dokumen tersebut melalui jalur penyelamatan yang berbahaya dan sangat berisiko di dalam kota yaitu melalui dari Museum Geologi ke Jalan Braga Nomor 3 ke Toko Onderling Belang kemudian ke Tasikmalaya, Solo, Magelang, dan akhirnya Jogjakarta.
Dalam melakukan penyelamatan tersebut, beliau dibantu oleh Amsir, Raden Prajitno, dan MMPurbo-Hadiwijoyo. Kantor jawatan terpaksa harus dipindah beberapa kali untuk menghindari agresi Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kantor jawatan sempat pindah ke Tasikmalaya lalu Magelang, dan Yogyakarta dari tempat awalnya di Bandung.
Kepahlawanan Arie Frederik Lasut tidak hanya terbatas melalui ilmu dan teknologi serta pada penyelamatan dokumen geologi dan tambang tetapi juga dengan berani mati berjuang di medan pertempuran di antara desing peluru sebagai Komandan Kompi BS (Berdiri Sendiri) Brigade 16, Kesatuan Reserse Umum X .
Arie Lasut beberapa kali menyerang pos Belanda dan merebut senjata dari tangan Belanda kemudian dibagi-bagi kepada anak buahnya dan digunakan untuk melawan Belanda.
Secara organisasi Arie Frederik Lasut turut aktif dalam organisasi Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) yang memiliki tujuan membela kemerdekaan Republik Indonesia.
Di bidang politik, kecerdasan serta semangat pantang menyerah menyebabkan beliau juga berjuang sebagai anggota delegasi Indonesia di meja perundingan yang dipimpin oleh Mr Mohamad Roem
Di samping itu Arie Lasut juga adalah anggota Komite Nasional, awal mula dewan perwakilan di Indonesia.
Peran Arie Frederik Lasut dalam perang melawan Belanda serta pengetahuannya tentang pertambangan dan geologi di Republik Indonesia, menyebabkan beliau menjadi incaran Belanda.
Segala cara digunakan baik bujukan maupun ancaman untuk membujuk/memaksa beliau mau bekerja sama dengan Belanda tetapi beliau tetap konsisten untuk tidak pernah mau bekerja sama dengan Belanda.
Pada pagi hari 7 Mei 1949 setelah berusaha menghindar dan melawan dengan tanpa senjata terhadap pasukan tentara Belanda bersenjata lengkap, dengan gagah berani Arie Frederik Lasut akhirnya berhasil ditangkap tentara Belanda dari rumahnya lalu dibawa ke Pakem, sekitar 7 kilometer di utara Yogyakarta.
Setelah ditangkap, dalam perjalanan menuju Pakem, Arie Frederik Lasut dipukul, disiksa dengan kejam agar mau memberitahukan rahasia negara berupa kekayaan tambang/geologi.
Penyiksaan kejam selama berjam-jam tersebut ternyata tidak membuat Arie Frederik Lasut berkhianat bagi negaranya, bagi tanah leluhurnya Toar Lumimuut, tapi justru memicu semangat berani mati untuk kejayaan Bangsa dan negara Indonesia!
Setelah dihajar dengan popor senjata, ditampar dan dipukul, serta disiksa habis-habisan, Arie Frederik Lasut tetap tidak mengeluarkan sepatah-katapun dari mulutnya.
Akhirnya sambil menatap tentara Belanda dengan gagah berani, beliau ditembak dengan keji oleh tentara Belanda yang putus asa.
Arie Frederik Lasut wafat di Pakem, Sleman, Yogyakarta, 7 Mei 1949 pada umur 30 tahun.
Beberapa bulan kemudian jenazah Arie Frederik Lasut dipindahkan ke pekuburan Kristen Kintelan di Yogyakarta di samping isterinya yang lebih dulu meninggal pada Desember 1947.
Upacara penguburan dihadiri pejabat presiden Republik Indonesia pada saat itu, Mr Assaat.
Arie Lasut mendapat penghargaan Pahlawan Pembela Kemerdekaan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 012/TK/TAHUN 1969 tentang Penetapan Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
4. Lambertus Nicodemus Palar
Lambertus Nicodemus Palar atau dikenal dengan LN Palar merupakan seorang pahlawan nasional yang lahir di Sulawesi Utara.
LN Palar merupakan tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di ranah perjuangan melalui diplomasi.
LN Palar dianugerahi gelar Pahlawan Nasional bertepatan pada hari pahlawan 10 November 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdasarkan Keppres No.68/TK/Tahun 2013, Tanggal 6 November 2013.
Selain LN Palar, pada kesempatan itu Presiden SBY juga menganugerahkan gelar pahlawan kepada dua tokoh lainnya yaitu Dr Radjiman Widyodiningrat dan TB Simatupang.
LN Palar dikenal sebagai tokoh yang unik sekaligus istimewa bagi Indonesia, ia adalah seorang tokoh yang sangat membumi meski menduduki sejumlah jabatan penting sebagai seorang diplomat.
Kehidupan Pribadi
LN Palar lahir Rurukan, Tomohon, Sulawesi Utara pada 5 Juni 1900.
LN Palar merupakan seorang anak dari pasangan suami istri Gerrit Palar, seorang penilik sekolah dan Jacoba Lumanauw.
LN Palar menikah dengan seorang perempuan bernama Johanna Petronella "Yoke" Volmers.
Dari pernikahan itu, LN Palar dikaruniai tiga orang anak, Mary Elizabeth Singh, Maesi Martowardojo, dan Bintoar Palar.
LN Palar meninggal di Jakarta pada 13 Februari 1981 dalam usia 80 tahun.
LN Palar dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Riwayat Pendidikan
LN Palar mengenyam pendidikan formal pertamanya di Meisjes School di Tomohon kemudian pindah ke Hoofd School di Tondano.
Lulus dari Hoofd School, LN Palar melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) antara 1916 sampai 1919.
LN Palar kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya ke Algemeene Middlebare School (AMS) di Yogyakarta.
Selama di Yogyakarta, LN Palar tinggal bersama Sam Ratulangi.
Setamat sekolah menengah, LN Palar melanjutkan ke Technische Hooge School (THS) di Bandung (sekarang ITB) pada tahun 1922 sampai 1923, namun LN Palar tidak sempat menyelesaikannya karena sakit.
Setelah pulih dari sakitnya, LN Palar kemudian pada 1924 melanjutkan kuliah ke Sekolah Tinggi Hukum (Rechts Hooge School) di Batavia.
Di Batavia inilah LN Palar mulai aktif dalam pergerakan nasional dengan bergabung dalam Jong Minahasa.
Pada 1926-1928, ia melanjutkan pendidikan di Gementelijke Universiteit di Amsterdam sembari bekerja di kota itu.
Riwayat Karier
LN Palar memulai kariernya ketika ia tinggal di Amsterdam, Belanda.
Pada 1930, LN Palar aktif menjadi anggota Social Democratische Arbeider Partij (SDAP) setelah dalam kongresnya menyebutkan hak kemerdekaan nasional untuk Hindia Belanda tanpa syarat.
Karier organisasinya terus melejit dengan menjabat sebagai sekretaris Komisi Kolonial SDAP dan Nederlands Verbond van Vakverenigingen pada Oktober 1933.
Selain di kedua organisasi itu, LN Palar juga menjabat sebagai direktur Perbureau Indonesia.
Melalui lembaga inilah, LN Palar mulai mengirimkan artikel-artikel tentang sosial demokrasi dari Belanda ke pers di Hindia Belanda.
Pada 1938, LN Palar datang ke Indonesia dan mengunjungi beberapa daerah untuk menghimpun informasi.
Dia memperoleh informasi bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia sedang giat-giatnya.
Sekembalinya ke Belanda, ia menuliskan pengalamannya di Indonesia, namun Perang Dunia II lebih dahulu berkecamuk dan Belanda diduduki oleh Jerman.
LN Palar tidak lagi bekerja untuk SDAP selama berkecamuknya perang, ia beraktivitas dalam laboratorium van der Waals, sembari mengajar Bahasa Melayu.
Selain itu, ia juga aktif dalam gerakan bawah tanah anti-Nazi Jerman.
Setelah PD II berakhir, LN Palar kembali aktif dalam kegiatan politik, ia aktif dalam Partij van de Arbeid (PvdA), partai baru yang sebelumnya berawal dari SDAP.
Melalui PvdA ini, LN Palar kemudian terpilih menjadi anggota Twede Kamer atau parlemen.
Setelah mendengar informasi kemerdekaan Indonesia, LN Palar mendukung pernyataan kemerdekaan Indonesia dan menjalin hubungan dengan para pemimpin Indonesia.
Namun sikap LN Palar ini kurang mendapat dukungan dari partainya.
Di parlemen, LN Palar juga mendesak pemerintah Belanda untuk menyelesaikan secara damai konflik Belanda-Indonesia tanpa adanya kekerasan bersenjata.
Namun pada 20 Juli 1947, parlemen menyetujui kebijakan Agresi Militer I untuk menyelesaikan konflik di Indonesia.
Setelah bertemu dengan Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya, seperti Sutan Sjahrir dan Agus Salim, LN Palar kemudian mengundurkan diri dari parlemen sebagai bentuk protes atas tindakan Belanda dalam Agresi Militer I.
Dari sinilah kontribusi LN Palar dalam perjuangan diplomasi Indonesia dimulai.
Pemerintah Indonesia kemudian memanggil LN Palar pulang untuk bersama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan.
Bersama Dr. Sudarsono dan Mr. Maramis, LN Palar ditugaskan oleh Mohammad Hatta dan Agus Salim selaku Menteri Luar Negeri untuk mendirikan Pemerintahan Indonesia dalam Pengasingan (Government in Exile) jika usaha Mr. Syafrudin Prawiranegara membuat PDRI di Bukit Tinggi gagal.
Perundingan-perundingan yang terjadi selama revolusi kemerdekaan tidak terlepas dari peran LN Palar.
LN Palar melakukan perundingan demi perundingan langsung di jantung diplomasio internasional di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat sesuai dengan perintah Soekarno yang memintanya menjadi juru bicara RI di PBB pada 1947.
Pada akhir 1947, LN Palar membuka kantor perwakilan RI di New York dibantu oleh Sudarpo, Soedjatmoko, dan Soemitro.
Sebelum pengakuan kedaulatan RI pada 1949, status LN Palar dan delegasi Indonesia di PBB adalah sebagai peninjau.
Namun setelah pengakuan kedaulatan kemerdekaan dan Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB pada 1950, LN Palar menjadi perwakilan resmi RI pertama dengan status keanggotaan penuh.
Setelah menjadi Kepala Perwakilan RI di PBB pada 1953, LN Palar kemudian menjadi Duta Besar RI untuk India dan memberikan kontribusi yang besar dalam persiapan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955.
Pada 1955, LN Palar dipanggil pulang ke Indonesia untuk membantu pelaksanaan KAA, yang dihadiri oleh 30 negara-negara Asia dan Afrika yang pada umumnya baru merdeka.
Usai KAA, LN Palar memulai kembali tugas diplomasinya dengan menjadi Duta Besar RI untuk Uni Soviet dan Jerman Timur selama dua tahun.
Kemudian pada 1957, LN Palar ditugasken menjadi Duta Besar RI untuk Kanada hingga tahun 1962.
Pada 1962 hingga 1965, LN Palar kembali menjadi Kepala Perwakilan RI di PBB.
Karena adanya konflik Indonesia-Malaysia, Presiden Soekarno kemudian mencabut keanggotaan RI di PBB.
Saat presiden Soekarno memutuskan keluar dari PBB, LN Palar kemudian menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.
Pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia meminta kembali masuk ke dalam keanggotaan PBB pada 1966.
Pengalaman LN Palar di PBB selama beberapa tahun sebelumnya, membuat ia menjadi utusan pemerintah pada 1966 usai perubahan politik di dalam negeri.
LN Palar pensiun dari tugas diplomatisnya pada 1968 setelah melayani bangsanya dalam permulaan usaha kemerdekaan, konflik Indonesia-Belanda melalui perjuangan diplomasinya.
Kahin dalam tulisannya menyebutkan jika LN Palar merupakan seorang diplomat senior yang memiliki pengalaman sangat panjang menjadi duta besar dan juga berjuang sebagai diplomat untuk negaranya.
Setelah pensiun, LN Palar masih memberikan kontribusi bagi pendidikan, pekerjaan sosial, dan juga penasihat perwakilan Indonesia di PBB.
LN Palar yang merupakan seorang putera terbaik Sulawesi Utara itu meninggal pada 12 Februari 1981 di usia 80 tahun.
5. Maria Walanda Maramis
Maria Josephine Catherina Maramis, atau yang lebih dikenal dengan nama Maria Walanda Maramis merupakan Pahlawan Nasional Indonesia.
Ia dikenal sebagai pahlawan yang berusaha memajukan keadaan wanita di Indonesia pada awal abad ke-20.
Seperti dilansir Tribunnews dari Wikipedia, sosok Maria Walanda Maramis dianggap sebagai pendobrak adat dan pejuang emansipasi wanita di dunia politik serta pendidikan.
Karena perjuangan dan dedikasinya, Maria diberi gelar Pahlawan Pergerakan Nasional dari pemerintah Indonesia pada 20 Mei 1969 silam.
Maria kecil menghabiskan sebagian besar waktunya di Minahasa Utara.
Lahir dari pasangan Maramis dan Sarah Rotinsulu, Maria merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara.
Namun pada usia enam tahun, Maria Walanda Maramis harus menjadi yatim piatu lantaran kedua orang tuanya jatuh sakit dan meninggal.
Maria kecil dan kedua saudaranya kemudian diasuh oleh sang paman dan dibawa ke Maumbi.
Bersama kakak perempuannya, Anatje, Maria kemudian disekolahkan sang paman di Sekolah Melayu.
Sekolah Melayu tersebut merupakan satu-satunya pendudukan resmi yang diterima Maria dan Anatje.
Pasalnya saat itu perempuan diharapkan untuk menikah dan mengasuh keluarga mereka.
Saat beranjak dewasa, Maria Walanda Maramis pindah ke Manado dan mulai menulis opini di surat kabar Tjahaja Siang.
Maria menuliskan soal pentingnya peran ibu dalam keluarga.
Ia juga menyebutkan ibu memiliki kewajiban untuk mengasuh dan menjaga kesehatan keluarganya.
Karena menyadari besarnya peran ibu dalam keluarga, Maria bersama beberapa orang mendirikan Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunannya (PIKAT) pada 8 Juli 1917.
Tujuan didirikannya PIKAT adalah untuk mendidik para wanita mengenai hal-hal rumah tangga, seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan lain sebagainya.
Di bawah pimpinan Maria Walanda Maramis, PIKAT berkembang pesat dan mulai mendirikan cabang di Maumbi, Tondano, dan Motoling.
Bahkan PIKAT juga memiliki beberapa cabang di Jawa, seperti di Batavia, Bogor, Bandung, Cimahi, Magelang, dan Surabaya.
Hampir satu tahun berdiri, PIKAT kemudian membuka sekolah di Manado pada 2 Juni 1918.
Hingga Maria meninggal pada 22 April 1924 di Maumbi, ia tetap aktif menjalankan PIKAT.
Untuk mengenang jasanya, pemerintah di Manado membangun Monumen Pahlawan Nasional Maria Walanda Maramis di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat.
Soal pembangunan monumen tersebut, diungkapkan kakak perempuan Maria, Anatje.
"(Monumen) Ini dibangun pada 8 Maret 1987 saat kepemimpinan Gubernur Rantung," ujar Anatje pada Jumat (26/2/2016), seperti dikutip dari TribunManado.co.id.
Saat diwawancarai TribunManado.co.id, Anatje memang tinggal di tempat peristirahatan terakhir Maria.
Jadi ia mengetahui bagaimana proses pembangunan Monumen Pahlawan Nasional Maria Walanda Maramis.
Tak hanya di Maumbi, patung Maria juga didirikan di Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang.
6. Pierre Tendean
Kapten Czi (Anumerta) Pierre Andreas Tendean, lahir pada 21 Februari 1939. Dia meninggal saat pemberontakan PKI pada 30 September 1965 atau wafat pada usia 26 tahun.
Dia mengawali karier militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution dengan pangkat letnan satu, ia dipromosikan menjadi kapten anumerta setelah kematiannya.
Pierre adalah anak dari Dokter AL Tendean asal Manado dan Maria Elizabeth Cornet, keturunan Indo-Perancis. Dia bahkan dijuluki "Robert Wagner dari Panorama" oleh gadis-gadis remaja Bandung.
Robert Wagner merupkan actor dan bintang film Amerika Serikat yang terkenal tahun 1960-an. Bumi Panorama, itulah sebutan untuk kampus Akademi Teknik Angkatan Darat.
Pierre adalah anak kedua dari tiga bersaudara, kakak dan adiknya bernama Mitze Farre dan Rooswidiati. Pierre mengenyam sekolah dasar di Magelang, lalu melanjutkan SMP dan SMA di Semarang tempat ayahnya bertugas.
Sejak kecil, ia sangat ingin menjadi tentara dan masuk akademi militer, namun orang tuanya ingin ia menjadi seorang dokter seperti ayahnya atau seorang insinyur.
Karena tekadnya yang kuat, ia pun berhasil bergabung dengan ATEKAD di Bandung pada 1958.
Dia bertugas memimpin sekelompok relawan di beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia. Pada 15 April 1965,
Pierre dipromosikan menjadi letnan satu, dan ditugaskan sebagai ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution.
Atas jasa-jasanya kepada negara, Kapten CZI TNI Anumerta Pierre Andreas Tendean dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi berdasarkan SK Presiden RI No. 111/KOTI/Tahun 1965, pada 5 Oktober 1965.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini diakui juga sebagai Pahlawan Nasional.
7. Robert Wolter Mongisidi
Robert Wolter Monginsidi di adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus pahlawan nasional Indonesia.
Ia lahir di Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, 14 Februari 1925 dan meninggal di Pacinang, Makassar, Sulawesi Selatan, 5 September 1949 pada umur 24 tahun.
Biografi
Robert merupakan anak dari Petrus Monginsidi dan Lina Suawa.
Dia memulai pendidikannya pada 1931 di sekolah dasar (bahasa Belanda: Hollands Inlandsche School atau (HIS), yang diikuti sekolah menengah (bahasa Belanda: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO) di Frater Don Bosco di Manado.
Kala itu, ia dididik sebagai guru Bahasa Jepang pada sebuah sekolah di Tomohon.
Setelah studinya, dia mengajar Bahasa Jepang di Liwutung, di Minahasa, dan di Luwuk, Sulawesi Tengah, sebelum ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan saat ia berada di Makassar.
Namun, Belanda berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas Indonesia setelah berakhirnya Perang Dunia II.
Mereka kembali melalui NICA (Netherlands Indies Civil Administration/Administrasi Sipil Hindia Belanda). Ia juga terlibat dalam perjuangan melawan NICA di Makassar.
Pada tanggal 17 Juli 1946, Monginsidi dengan Ranggong Daeng Romo dan lainnya membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS), yang selanjutnya melecehkan dan menyarang posisi Belanda.
Dia ditangkap oleh Belanda pada 28 Februari 1947, tetapi berhasil kabur pada 27 Oktober 1947. Belanda menangkapnya kembali dan kali ini Belanda menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Mongisidi dieksekusi oleh tim penembak pada 5 September 1949.
Jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Makassar pada 10 November 1950.
Penghargaan
Robert Wolter Mongisidi dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia pada 6 November, 1973.
Dia juga mendapatkan penghargaan tertinggi Negara Indonesia, Bintang Mahaputra (Adipradana), pada 10 November 1973.
Ayahnya, Petrus, yang berusia 80 tahun pada saat itu, menerima penghargaan tersebut.
Bandara Wolter Monginsidi di Kendari, Sulawesi Tenggara dinamakan sebagai penghargaan kepada Monginsidi, seperti kapal Angkatan Darat Indonesia, KRI Wolter Monginsidi dan Yonif 720/Wolter Monginsidi.
Biodata
Nama lengkap: Robert Wolter Monginsidi
Tempat, tanggal lahir: Manado, Sulawesi Utara, 14 Februari 1925
Meninggal: Makassar 5 September 1949
8. Sam Ratulangi
Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau dikenal dengan Sam Ratulangi lahir pada tanggal 5 November 1890 di Tondano, Minahasa.
Sam Ratulangi adalah putra Jozias Ratulangi dan Augustina Gerungan.
Jozias Ratulangi adalah guru Hoofden School atau sekolah menengah untuk anak-anak dari kepala-kepala desa di Tondano.
Augustina Gerungan putri Kepala Distrik Tondano-Touliang, Jacob Gerungan. (1)
Pendidikan
Sam Ratulangi mengawali pendidikannya di Tondano yaitu sekolah dasar Belanda, Europeesche Lagere School, lalu melanjutkan pendidikan ke Hoofden School.
Pada 1904, Sam Ratulangi berangkat ke Jawa bersekolah di Sekolah Pendidikan Dokter Hindia (STOVIA) dengan beasiswa.
Namun sesampainya di Batavia, Sam Ratulangi berubah pikiran dan memutuskan untuk belajar di sekolah menengah teknik Koningin Wilhelmina.
Sam Ratulangi lulus pada 1908 dan mulai bekerja pada konstruksi rel kereta api di daerah Priangan di Jawa Barat.
Pada 1911, Sam Ratulangi kembali ke Minahasa, karenasang Ibu sakit parah yang kemudian meninggal dunia pada 19 November 1911.
Sedangkan sang Ayahnya sudah meninggal dunia sewaktu Sam Ratulangi berada di Jawa.
Setelah kematian sang Ibu mereka, Sam Ratulangi dan kedua saudara perempuannya membagi warisan orang tua mereka.
Sam Ratulangi menggunakan uang yang dia terima untuk membiayai pendidikannya di Eropa.
Pada 1915, Sam Ratulangi berhasil memperoleh ijazah guru ilmu pasti atau Middelbare Acte Wiskunde en Paedagogiek dari Universitas Amsterdam, Belanda.
Pada 1919, Sam Ratulangi memperoleh gelar Doktor der Natur-Philosophie (Dr Phil) untuk Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dari Universitas Zurich.
Sam Ratulangi dikenal dengan filsafatnya: "Si tou timou tumou tou" yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia, jika sudah dapat memanusiakan manusia.
Sosok paholawan nasional, Sam Ratulangi (biografi-pahlawan-nasional-indonesia.blogspot.com)
Perjuangan
Selama mengenyam pendidikan di Amsterdam, Belanda, Sam Ratulangi sering bertemu dengan saudara RA Kartini, Sosro Kartono dan tiga pendiri National Indische Partij, Ernest Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryoningrat.
Sam Ratulangi juga aktif dalam organisasi Indische Vereeniging, atau Perhimpunan Indonesia dan terpilih sebagai ketua pada 1914.
Sam Ratulangi juga aktif dalam menulis artikel, satu diantaranya berjudul 'Sarekat Islam' yang diterbitkan di Onze Kolonien pada 1913.
Sam Ratulangi menulis tentang pertumbuhan koperasi pedagang lokal Sarekat Islam dan juga memuji gerakan Budi Utomo di Indonesia.
Setelah kembali ke Indonesia pada1919, Sam Ratulangi pindah ke Yogyakarta untuk mengajar matematika dan sains di sekolah teknik Prinses Juliana School.
Setelah tiga tahun mengajar Sam Ratulangi kemudian pindah ke Bandung dan memulai perusahaan asuransi Assurantie Maatschappij Indonesia dengan seorang dokter yang juga berasal dari Minahasa, Roland Tumbelaka.
Pada 1923, Sam Ratulangi menjadi sekretaris badan perwakilan daerah Minahasa di Manado (Minahasa Raad) pada 1924 -1927.
Selama di Minahasa Raad, Sam Ratulangi memperjuangkan hak untuk orang-orang Minahasa, misalnya membuat pemerintah kolonial menghapuskan kerja paksa di Minahasa.
Pada 16 Agustus 1927 Sam Ratulangi dan Roland Tumbelaka memulai partai Persatuan Minahasa yang beranggotakan orang-orang sipil dan militer.
Namun beberapa anggota militer melakukan pemberontakan dan melawan Belanda sehingga karena hal tersebut partai dilarang berpartisipasi dalam organisasi politik.
Sam Ratulangi dan Roland Tumbelaka kemudian kembali partai Persatuan Minahasa yang hanya memiliki anggota sipil.
Pada 1939, Persatuan Minahasa merupakan satu diantara partai politik yang membentuk Gabungan Politik Indonesia bersama Gerindo, Parindra, Pasundan, PPKI (Persatuan Partai Katolik Indonesia), dan PSII (Persatuan Sarekat Islam Indonesia).
Pada 1927-1937 Sam Ratulangi diangkat menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat mewakili rakyat di Minahasa.
Jabatannya di Dewan Rakyat tersebut digunakan untuk mengajukan tuntutan supaya kolonial Belanda menghapuskan segala perbedaan dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan antara orang-orang Belanda dan pribumi.
Pada 1932 Sam Ratulangi adalah satu dari pendiri Vereniging van Indonesische Academici atau Persatuan Cendekiwan Indonesia.
Pada 1938, Sam Ratulangi menjadi editor sebuah majalah berita berbahasa Belanda, Nationale Commentaren kemudian menulis pendapat-pendapat yang menentang tindakan tidak adil pemerintah kolonial Belanda.
Di masa pendudukan Jepang, Sam Ratulangi ikut terlibat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada awal Agustus 1945, mewaliki Sulawesi
Setelah Kemerdekaan
Ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Sam Ratulangi diangkat sebagai gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Ujung Pandang.
Namun pada bulan September, pasukan Belanda bersama Netherlands Indies Civiele Administration (NICA) atau pemerintahan sipil hindia Belanda mendarat di Makassar untuk mengambil alih pemerintahan.
Sam Ratulangi yang tidak terima dengan keputusan tersebut kemudian mendirikan Pusat Keselamatan Rakyat sebagai bentuk perlawanan bersama rakyat.
Perebutan kekuasaan terjadi antara pihak Belanda dan rakyat, hingga menimbulkan pemberontakan.
Kemudian pada 5 April 1946, Sam Ratulangi beserta para pengikutnya dipenjarakan selama satu bulan di Ujung Pandang sebelum dibuang ke Serui, Irian Jaya.
Di tempat pengasingannnya di Serui, Irian Jaya, Sam Ratulangi membentuk organisasi Ibunda Irian dan Partai Kemerdekaan Irian yang bertujuan memupuk semangat kemerdekaaan.
Setelah adanya perjanjian Renville pada 1948, Sam Ratulangi akhirnya dibebaskan kemudian ditunjuk oleh Soekarno menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan delegasi Indonesia dalam perundingannya dengan Belanda. (1)
Pada 10 November 1948 ketika terjadi pemecahbelahan persatuan bangsa Indonesia, Sam Ratulangi mengeluarkan Manifes Ratulangi.
Isinya adalah pernyataan keras dari Sam Ratulangi yang menentang Indonesia bagian Timur dari Republik Indonesia.
Wafat
Sam Ratulangi meninggal dunia pada 30 Juni 1949 dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum pada 23 Juli 1949, jenazahnya dipindahkan ke Manado.
Pada 1961, Sam Ratulangi diberi anugrah dengan gelar Pahlawan Nasional Indonesia melalui Keppres No. 590 Tahun 1961.
Nama Sam Ratulangi dapat ditemukan pada nama jalan di Minahasa, misalnya di Bitung, Manado, Tomohon, dan Tondano.
Nama Sam Ratulangi juga dipakai sebagai nama bandar udara internasional Manado dan universitas negeri di Manado.
Bahkan di sebuah taman kota di Davao, Filipina juga terdapat patung Sam Ratulangi.
Pada 2016, Kementerian Keuangan mengeluarkan uang baru seri 2016 di mana pecahan Rp 20.000 memiliki gambar Sam Ratulangi di bagian depan.
9. Bernard Wilhelm Lapian
Bernard Wilhelm Lapian. Lapian lahir di Kawangkoan 30 Juni 1892.
Ia wafat di Jakarta pada 5 April 1977 dalam usia 84 tahun.Lapian punya banyak julukan. Dari pahlawan tiga zaman hingga sang nasionalis religius. Wajar saja.
Karena kiprah Lapian terentang sejak masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang hingga zaman kemerdekaan Indonesia. Lapangan perjuangannya pun terbentang luas dari aktivis pejuang, militer, birokrasi, jurnalistik hingga keagamaan.
Seperti dituturkan Judie Turambi, ketua Panitia mengutip sejumlah buku tentang BW Lapian, Lapian muda adalah salah satu tokoh yang menggunakan jurnalisme sebagai alat perjuangan.
Ketajaman pena Lapian mulai terlihat saat ia menulis di surat kabar lokal Magelang "Pangkal Kemadjoean". Lapian menulis tentang penindasan yang dialami warga Magelang.
Tulisan semacam itu tergolong langka di masa itu, yakni tahun 1919 dimana Belanda masih berkuasa penuh. Lapian kian bergelut dengan jurnalisme ketika menjabat ketua cabang Persatuan Minahasa di Batavia.
Dia membidani lahirnya surat kabar "Fajar Kemadjoean". Lapian leluasa menyampaikan idenya tentang Indonesia merdeka melalui surat kabar itu.
Tulisan Lapian yang keras menentang penjajah turut andil dalam menyemai nasionalisme di masa itu, yang ditandai dengan Sumpah Pemuda.
Jelang perang dunia 2, nasionalisme di Minahasa menurun. Mereka termakan propaganda Belanda untuk memasukkan Minahasa sebagai provinsi ke 12 Belanda.
Ia mendirikan surat kabar Semangat Hidup untuk melawan propaganda Belanda itu.
Menurut Turambi, pengalaman berorganisasi serta di dunia pers menumbuhkan sikap demokratis pada Lapian. Hal itu tampak saat ia menjadi anggota Volksraaad Minahasa tahun 1930.
Umumnya anggota Volksraad menampilkan sikap feodalistik.
"Namun Lapian mampu menunjukkan sikap demokratis," kata dia. Sikap hidup yang demokratis, membawa Lapian ke kongres pemuda dimana sumpah pemuda tercetus.
Puncak perjuangan Lapian adalah peristiwa merah putih di Manado.
Dikisahkan pada 7 Januari 1946, Lapian yang waktu itu menjabat sebagai Wali kota Manado didatangi para nasionalis antaranya Tumbelaka, Taulu serta Wuisan.
Mereka memberitahu Lapian rencana mengadakan perebutan kekuasaan. Lapian setuju namun menyuruh keduanya bergerak diam - diam.
Diputuskan hari H pada 14 Februari. Namun rencana itu tercium Belanda. Buktinya Ch Taulu serta Wuisan ditangkap oleh tentara Belanda sehari sebelum hari h. Meski demikian rencana perebutan kekuasaan terus berlanjut.
Dimulai pukul 1 dinihari, dua jam kemudian bendera merah putih sudah berkibar di tangsi Belanda di Teling.
Peristiwa bersejarah itu menjadi headline sejumlah pers barat antaranya Radio Australia, BBC London serta surat kabar dari Amerika.
Radio Australia bahkan menyiarkan pidato Presiden Sukarno tentang peristiwa itu.
"Minahasa walaupun terkecil dan terpencil di wilayah republik Indonesia, namun putra putrinya telah memperlihatkan kesatriaan terhadap panggilan ibu pertiwi, laksanakan tugasmu dengan seksama dan penuh tanggung jawab," kata Sukarno.
Surat kabar terbesar waktu itu di Indonesia Merdeka menulis peristiwa itu dengan judul "Pemberontakan besar di Minahasa".
Dua hari setelah penyerbuan yang berani itu, CH Taulu yang menjadi pimpinan tertinggi tentara republik indonesia Sulawesi utara menggelar rapat di kantor Dewan Minahasa di Manado.
Rapat dihadiri pembesar militer sipil, hukum tua di Minahasa, raja Bolmong serta kepala daerah Gorontalo.
Disepakati pembentukan Dewan musyawarah masyarakat Sulut dengan Lapian menjadi kepala pemerintahan sipil Sulut.
Setelah diangkat, Lapian langsung melakukan sejumlah langkah progresif. Pada 21 Februari, Lapian mengumumkan wilayah Sulut serta tengah, bekas residen Manado adalah bagian dari pemerintah republik Indonesia.
Lapian juga berupaya menentramkan rakyat serta membenahi administrasi pemerintahan. Lewat tipu muslihat Belanda kembali merebut kekuasaan.
Pada 11 Maret 1946, Lapian ditangkap lalu dipenjara di tangsi Teling. Setahun kemudian ia dipenjara di Cipinang. Pada 1948, Lapian dibawa ke penjara Sukamiskin.
Setahun kemudian ia dibebaskan bersamaan dengan penyerahan kedaulatan. Oleh pemerintahan Sukarno, ia diangkat sebagai Gubernur Sulawesi.
Tugasnya tak ringan. Membereskan Kahar Muzakar.
Lapian bersama seorang anaknya melakukan langkah berani dengan menemui Kahar Muzakar di tempat persembunyian.
Ia berangkat tengah malam. Kembali ke rumah Gubernur tiga hari kemudian. Lapian juga berhasil merintis pemilu di Minahasa.
Pernjuangan Lapian membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda juga terjadi di lapangan keagamaan.
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, semua Gereja Kristen berada di bawah naungan satu institusi Indische Kerk yang dikendalikan oleh pemerintah.
Karena berafiliasi dengan pemerintah, Gereja zaman itu mau tak mau bersikap kompromi dengan penjajahan.
Tak ada suara kenabian, padahal masyarakat begitu tertindas.
BW Lapian bersama tokoh-tokoh lainnya kemudian mendeklarasikan berdikarinya Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) tahun 1933, yaitu suatu gereja mandiri hasil bentukan putra-putri bangsa sendiri yang tidak bernaung di dalam Indische Kerk. (Berbagai Sumber/Aldi Ponge).
#Pahlawan Nasional asal Manado, Ada Dijuluki 'Hantu Laut' Ditakuti Belanda hingga Gugur Usia 24 Tahun