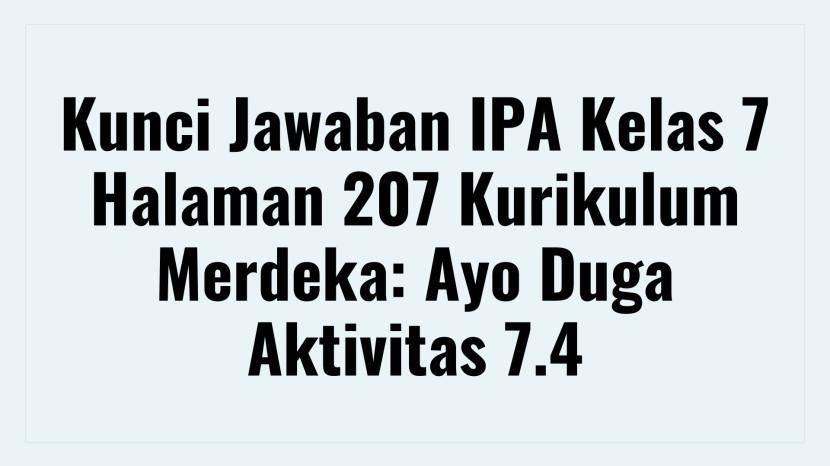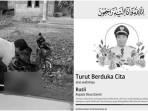Hari HAM Sedunia
Hari HAM Sedunia, Berikut Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu
Hari HAM Sedunia, Berikut Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu
TRIBUNMANADO.CO.ID - 10 Desember merupakan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia,
Peringatan ini rutin dirayakan setiap tahunnya oleh banyak negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Sejarah Hari Hak Asasi Manusia pada bagian akhir artikel ini.
Tapi bagaimana penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) hingga peringatan Hari Hak Asasi Manusia 2018?
Baca: Fakta-fakta Gelaran Liga 1 2018, Isu Pengaturan Skor hingga Pemukulan Anak Menpora
Beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum juga menemukan titik terang terkait penyelesaiannya.
Sampai saat ini, masih ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang ‘tertahan’ di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Tujuh kasus itu Tragedi 1965, Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Kasus Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998.
Baca: 6 Napi Pembunuh yang Masih Buron Setelah Kabur dari LP Banda Aceh, 2 Divonis Mati
Kerusuhan Mei 1998, Penembakan Trisakti, Tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II (1998-1999), serta Kasus Wasior dan Wamena di Papua (2000). Adapula kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
Berikut ini catatan terkait konflik dan polemik HAM yang terjadi sepanjang dua dasawarsa terakhir, dikutip dari dokumentasi harian Kompas, Kompas.com, dan sumber kredibel lain:
Pelanggaran HAM Berat 1996-1999
Proses untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru terbilang tidak mudah. Ada pengorbanan besar saat menyuarakan protes terhadap Soeharto kala itu.
Aksi demonstrasi yang berujung mundurnya Soeharto dari jabatan presiden dapat dibilang akumulasi ‘kekesalan terpendam’ masyarakat atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi sepanjang dua tahun terakhir kekuasaan "The Smiling General" itu.

Namun, setelah Soeharto jatuh masih saja terjadi sejumlah catatan hitam pelanggaran HAM dalam mengatasi aksi demonstrasi mahasiswa pada 1999.
Aksi represif aparat keamanan disertai penembakan menyebabkan Tragedi Semanggi I dan Semanggi II yang menewaskan sejumlah mahasiswa.
Kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli

PERISTIWA Sabtu Kelabu 27 Juli 1996 menjadi momentum yang diingat masyarakat. Aksi penyerangan terhadap kantor Partai Demokrasi Indonesia yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri saat itu menimbulkan korban jiwa akibat intervensi kekuasaan yang mengakibatkan dualisme partai politik.
Hasil penyidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, kerusuhan tersebut mengakibatkan lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar.
Rezim Orde Baru kemudian menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang Peristiwa 27 Juli 1996. Setelah itu, terjadilah kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.
Berdasarkan laporan penyelidikan Tim Ad Hoc Komnas HAM, setidaknya 23 aktivis pro demokrasi menjadi korban. Hingga sekarang, sembilan orang dikembalikan, satu orang meninggal dunia, dan 13 orang masih hilang.
Tragedi Mei 1998
Pelanggaran HAM kembali terjadi saat aparat keamanan bersikap represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa di depan kampus Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dan ratusan mahasiswa lain terluka akibat tembakan dengan menggunakan peluru tajam.
Aktivis HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2017) silam.
Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa telah berlangsung selama 10 tahun sejak aksi pertama di depan Istana Merdeka pada 18 Januari 2007.
Sehari setelahnya, muncul tragedi lain, yaitu Kerusuhan 13–15 Mei 1998. Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis Tionghoa.
Tragedi Semanggi I
Tragedi ini terjadi pada 13 November 1998. Saat itu mahasiswa berdemonstrasi menolak Sidang Istimewa MPR yang dinilai inkonstitusional, menuntut dihapusnya dwifungsi ABRI, dan meminta Presiden segera mengatasi krisis ekonomi.
Mahasiswa yang melakukan demonstrasi di sekitar kampus Universitas Atma Jaya, Semanggi, Jakarta, dihalangi aparat bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Ketika mahasiswa mencoba bertahan, tiba-tiba terjadi penembakan oleh aparat.
Setidaknya lima orang mahasiswa menjadi korban. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya BR Norma Irmawan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Engkus Kusnadi, dan mahasiswa Universitas Terbuka Heru Sudibyo.
Kemudian, mahasiswa universitas Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Sigit Prasetyo dan mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (ITI) Teddy Wardani Kusuma.
Peristiwa ini juga melukai sebanyak 253 orang lainnya. Setidaknya lima orang mahasiswa menjadi korban.
Mereka adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya BR Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Engkus Kusnadi, dan mahasiswa Universitas Terbuka Heru Sudibyo.
Kemudian, mahasiswa universitas Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Sigit Prasetyo dan mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (ITI) Teddy Wardani Kusuma. Peristiwa ini juga melukai sebanyak 253 orang lainnya.
Tragedi Semanggi II
Peristiwa ini terjadi pada 24 September 1999, saat mahasiswa menolak rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Aturan yang sedianya akan menggantikan UU Subversi tersebut dianggap terlalu otoriter.
Lagi-lagi, aksi penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa kembali menelan korban. Tercatat 11 orang meninggal dunia akibat penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Salah satu korbannya adalah Yap Yun Hap, mahasiswa Universitas Indonesia. Yap Yun Hap tertembak tepat di depan kampus Atma Jaya Jakarta.
Hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) pada Maret 2002 menyatakan bahwa ketiga tragedi tersebut bertautan satu sama lain.
KPP HAM TSS juga menyatakan, “…terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat HAM yang antara lain berupa pembunuhan, peganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas…”.
Komnas HAM melalui KPP HAM TSS merekomendasikan untuk melanjutkan penyidikan terhadap sejumlah petinggi TNI/POLRI pada masa itu. Namun, hingga saat ini Kejaksaan Agung belum meneruskan berkas penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan.
Polemik Papua
SELAMA era Orde Baru, Papua sering kali dianggap sebagai provinsi yang kurang mendapat perhatian. Padahal, Papua menghasilkan sejumlah kekayaan alam yang menjadi sumber penghasilan negara.
Saat era reformasi berjalan, sejumlah perubahan sebenarnya telah dilakukan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanahkan otonomi daerah memberikan sejumlah keistimewaan bagi Papua.
Wilayah yang kini terdiri dari dua provinsi, Papua dan Papua Barat, kemudian mendapat status daerah dengan otonomi khusus sejak 2001.
Namun, masih terdapat sejumlah masalah, terutama terkait pelanggaran HAM. Berikut ini catatannya.
Peristiwa Waisor dan Wamena
Pada periode 1998 hingga 2016, tercatat lima kasus pelanggaranberat HAM terjadi di Papua.
Lima kasus itu adalah kasus Biak Numfor pada Juli 1998, peristiwa Wasior pada 2001, peristiwa Wamena pada 2003, peristiwa Paniai pada 2014, dan kasus Mapenduma pada Desember 2016.
Secara umum, kasus pelanggaran HAM itu terkait cara aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi masyarakat Papua. Isu disintegrasi yang membayangi Papua memperparah keadaan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah memprioritaskan penyelesaian lima kasus pelanggaran berat HAM tersebut.
Wiranto menjelaskan, penanganan kasus Wasior dan Wamena saat ini berada dalam koordinasi Komnas HAM bersama Kejaksaan Agung.
Jaksa Agung telah mengembalikan berkas penyelidikan kepada Komnas HAM selaku penyelidik agar mereka melengkapi berkas penyelidikan yang belum lengkap terkait pelaku, korban baik dari sipil maupun kelompok separatis bersenjata, visum et repertum korban, dukungan ahli forensik, dan dokumen Surat Perintah Operasi.
Adapun untuk kasus Paniai, Mapenduma, dan peristiwa Biak Numfor, penanganannya masih berada dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM.
Kasus Pembunuhan Theys
Pada 10 November 2001, Theys Hiyo Eluay dan sopirnya, Aristoteles Masoka, dikabarkan hilang dan diculik oleh orang tak dikenal. Theys merupakan Ketua Presidium Dewan Papua.
Sehari kemudian, Theys ditemukan tewas di dalam mobilnya di Skouw, tak jauh dari perbatasan RI-Papua Niugini. Adapun Aristoteles Masoka sampai sekarang belum ditemukan.
Kematian Theys merupakan kasus yang diduga sarat dengan motif politik dan kepentingan. Berdasarkan catatan Kontras, ada beberapa hal yang berkaitan erat dengan peristiwa pembunuhan tersebut.
Pertama, dokumen Departemen Dalam Negeri (Juni 2000) tentang rencana operasi pengondisian wilayah dan pengembangan jaringan komunikasi dalam menyikapi arah politik Papua untuk merdeka.
Kedua, fakta di lapangan menunjukkan ada peningkatan kekerasan sampai kematian Theys, dan kekerasan menurun drastis setelah pembunuhan tersebut.
Terkait kasus ini, tujuh anggota TNI dihadapkan ke pengadilan militer. Tujuh terdakwa yang disidangkan di Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya, Rabu 5 Maret 2003.
Ketujuh terdakwa itu adalah Letkol (Inf) Hartomo, Mayor (Inf) Donni Hutabarat, Kapten (Inf) Rionardo, Lettu (Inf) Agus Suprianto, Sertu Asrial, Sertu Laurensius LI, dan Praka Achmad Zulfahmi.
Oditur Militer menuntut mereka hukuman 2-3 tahun penjara. Dalam sidang, Oditur Militer menyatakan para terdakwa terbukti bersalah.
Namun, elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP) menilai proses pengadilan yang berlangsung merupakan upaya memutus rantai komando saja, bertentangan dengan prinsip imparsial, dan hanya digunakan untuk mengukuhkan impunitas aparat militer yang terlibat.
Pada 2014, Komnas HAM mulai membuka kembali masalah pembunuhan Theys dan hilangnya Aristoteles Masoka.
Komnas HAM mempelajari salinan berkas dari Pengadilan Mahkamah Militer terkait kasus 13 tahun sebelumnya itu. Dari salinan berkas terungkap, para pelaku pembunuh Theys mengakui bahwa mereka sedang melaksanakan tugas negara.
Hal lain yang didapatkan dari berkas tersebut, Theys disiksa terlebih dahulu sebelum dieksekusi.
Pembunuhan Munir

HINGGA saat ini, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib masih menjadi misteri. Aktivis yang akrab disapa Cak Munir itu meninggal dunia pada 7 September 2004.
Munir diracun dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta menuju Amsterdam, yang transit di Singapura.
Saat itu, pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu hendak melanjutkan jenjang pendidikan di Belanda. Proses peradilan telah dilakukan untuk mengadili pelaku pembunuhan Munir.
Dalam kasus ini, pengadilan telah menjatuhkan vonis 14 tahun penjara terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda yang saat itu sedang cuti tetapi ada di penerbangan yang sama dengan Munir, sebagai pelaku pembunuhan Munir.
Sejumlah fakta persidangan juga menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kasus pembunuhan ini.
Namun, pada 13 Desember 2008, mantan Deputi V BIN Mayjen Purn Muchdi Purwoprandjono yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini divonis bebas dari segala dakwaan.
Belasan tahun berselang, istri almarhum Munir, Suciwati, dan para aktivis HAM lainnya tetap meminta pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut dan mengungkap siapa yang menjadi dalang sebenarnya.
Menurut Suciwati, Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan menuntaskan kasus Munir saat mengundang 22 pakar hukum dan HAM pada 22 September 2016.
Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi—sebutan atau panggilan untuk Joko Widodo—menunjuk dan meminta Jaksa Agung segera bekerja menindaklanjuti kasus Munir berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus kematian Munir.
Namun, hingga saat ini, Suciwati menilai pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab meski Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan informasi dan meminta pemerintah mengumumkan hasil investigasi TPF.
Upaya Suciwati dan Kontras berlanjut pada gugatan ke KIP. Dalam sidang putusan, KIP menyatakan bahwa pemerintah diminta segera mengumumkan hasil penyelidikan TPF kasus kematian Munir seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, yakni Kontras.
Kemudian, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengajukan banding atas putusan tersebut. PTUN Jakarta mengabulkan banding itu.
Atas Putusan PTUN, Kontras mengajukan kasasi ke MA pada 27 Februari 2017. MA memutuskan menolak kasasi tersebut.
Hingga saat ini belum diketahui alasan pembunuhan Munir. Sejauh ini, dugaan yang muncul adalah pembunuhan terkait upaya Munir dalam mengungkap dan menuntut pertanggungjawaban atas sejumlah pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Sejarah Hari Hak Asasi Manusia (HAM)
Sejarah awal Hari Hak Asasi Manusia ketika Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 silam.
Hari Hak Asasi Manusia secara formal dan rutin diperingati dimulai sejak tahun 1950.
Setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi mengundang semua Negara dan organisasi yang peduli untuk ikut pula mengadopsi merayakan Hari Hak Asasi Manusia setiap tanggal 10 Desember.
TONTON JUGA:
TAUTAN AWAL: https://nasional.kompas.com/jeo/konflik-dan-pelanggaran-ham-catatan-kelam-20-tahun-reformasi