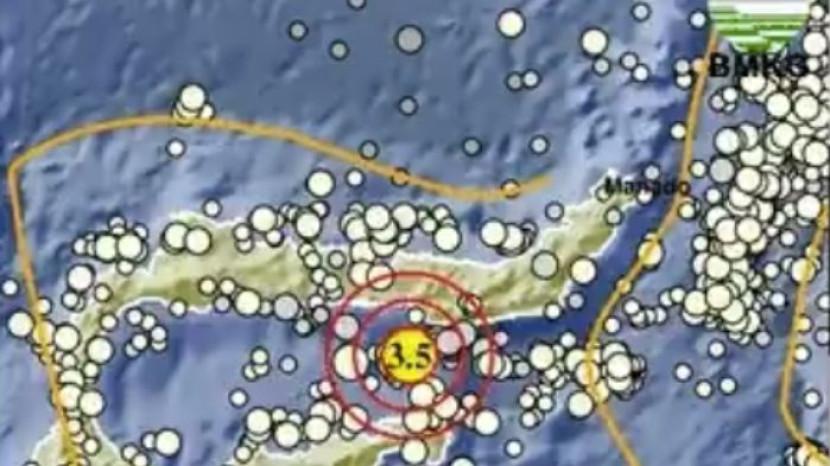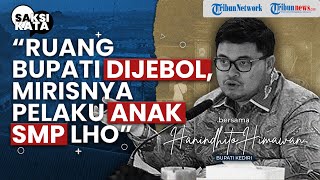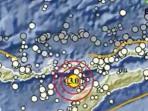Suku Baduy
Sejarah Suku Baduy, Kelompok yang Pegang Teguh Tradisi, Tolak Membangun Sekolah Modern
Suku Baduy a merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rhendi Umar
TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) kembali mengenakan pakaian adat saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Senin (16/8/2021).
Presiden Jokowi kembali mengenakan pakain adat dan kali ini adalah baju adat Baduy, Banten.
Pakaian tersebut disiapkan oleh Jaro Saija, Tetua Adat Masyarakat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes, Leuwidamar, Banten.
Jokowi mengaku menyukai pakaian adat Baduy tersebut lantaran memiliki desain sederhana dan simpel serta nyaman dipakai.
"Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai," kata Presiden Jokowi sebelum menutup pidatonya.
"Saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada Pak Jaro Saija, Tetua Adat Masyarakat Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini," ucap Jokowi.

Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat Suku Baduy di Sidang Tahunan MPR RI, Senin (16/8/2021). (Youtube Sekretariat Presiden)
Diketahui Suku Badui atau kadang sering disebut Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Populasi mereka sekitar 26.000 orang, mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar.
Selain itu mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Badui Dalam.
Secara etnis Baduy termasuk dalam suku bangsa Sunda, mereka dianggap sebagai atau suku Sunda pedalaman yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar.
Masyarakat Badui menolak istilah "wisata" atau "pariwisata" untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka.
Sejak 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah "Saba Budaya Baduy", yang bermakna "Silaturahmi Kebudayaan Badui".
Sebutan "Baduy" merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden).
Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut.
Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai urang Kanekes atau "orang Kanekes" sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeo (Garna, 1993).
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang tepat adalah "Badui" dan bukan "Baduy".
Bahasa yang mereka gunakan adalah Bahasa Sunda. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar mereka lancar menggunakan Bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah.
Orang Kanekes Dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat-istiadat, kepercayaan/agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja.
Orang Kanekes tidak mengenal sekolah, karena pendidikan formal berlawanan dengan adat-istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka.
Bahkan hingga hari ini, walaupun sejak era Soeharto pemerintah telah berusaha memaksa mereka untuk mengubah cara hidup mereka dan membangun fasilitas sekolah modern di wilayah mereka, orang Kanekes masih menolak usaha pemerintah tersebut.
Namun masyarakat Kanekes memiliki caranya sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka hingga sepadan dengan masyarakat di luar suku Badui.
Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari tujuh dewa atau batara yang diutus ke bumi.
Asal usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama.
Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga Kanekes, mempunyai tugas bertapa atau asketik (mandita) untuk menjaga harmoni dunia.

Suku Baduy (istimewa/tribunnewswiki)
Pendapat mengenai asal usul orang Kanekes berbeda dengan pendapat para ahli sejarah, yang mendasarkan pendapatnya dengan cara sintesis dari beberapa bukti sejarah berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta cerita rakyat mengenai 'Tatar Sunda' yang cukup minim keberadaannya.
Masyarakat Kanekes dikaitkan dengan Kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran (sekitar Bogor sekarang). Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ujung barat pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari Kerajaan Sunda.
Banten merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu, dan ramai digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman.
Dengan demikian penguasa wilayah tersebut, yang disebut sebagai Pangeran Pucuk Umun menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan.
Untuk itu diperintahkanlah sepasukan tentara kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut.
Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut tampaknya menjadi cikal bakal Masyarakat Kanekes yang sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut (Adimihardja, 2000).
Perbedaan pendapat tersebut membawa kepada dugaan bahwa pada masa yang lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup, yang mungkin adalah untuk melindungi komunitas Kanekes sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran.
Warga Baduy dikenal dengan kelompok yang masih memegang teguh tradisi. Salah satunya adalah upacara adat kawalu.
Kawalu merupakan ungkapan rasa syukur atas keberhasilan pertanian yang diwujudkan dengan berpuasa.
Upacara adat ini merupakan salah satu cara mereka menjaga pikukuh karuhun.
Dalam tulisannya, Seba, Puncak Ritual Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Nandang Rusnandar, yang mengutip Kurnia, menyampaikan bahwa pikukuh karuhun ialah doktrin yang mewajibkan mereka melakukan berbagai hal sebagai amanat leluhurnya.
Dilaksanakan tiga kali setahun
Masyarakat Baduy melaksanakan kawalu sebanyak tiga kali dalam setahun, yakni pada bulan Kasa, Karo, dan Katiga.
Makna dari puasa ini adalah untuk membersihkan diri dari hawa nafsu yang buruk.
Di bulan Kasa, mereka melakukan kawalu tembey atau kawalu awal. Pada tanggal 16, seluruh masyarakat Baduy akan berpuasa. Puasa ini dilakukan sehari semalam hingga tanggal 17.
Di tanggal tersebut, mereka bakal berganti pakaian dengan yang baru dan bersih. Lalu sederet ritual dilakukan, seperti membuat saji (khusus wanita), mandi di sungai, pembacaan mantera oleh puun (ketua adat Baduy), dan diakhiri dengan makan saji (buka puasa).
Puasa di bulan Karo disebut kawalu tengah, sedangkan di bulan Katiga dinamakan kawalu tutug.
Ritual ngalaksa
Di kawalu tutug, warga Baduy, baik tungtu (Baduy Dalam) dan panamping (Baduy Luar), menggelar ritual ngalaksa atau membuat makanan khas laksa. Prosesi ini dilakukan oleh ibu-ibu.
Endang Supriatna dalam tulisannya Upacara Seba pada Masyarakat Baduy menjelaskan, laksa merupakan makanan berbahan tepung beras yang dibentuk seperti mi, lalu dicetak ke dalam tempat adonan yang dinamai sangku.
Nandang menuliskan, orang-orang yang membuat laksa haruslah yang berhati bersih dan jujur.
Saat melangsungkan ngalaksa, warga Baduy memanfaatkannya untuk menghitung jumlah warga.
Caranya, setiap kepala keluarga wajib menyerahkan ikatan tangkai padi sesuai dengan jumlah anggota keluarganya kepada kokolot (tetua) kampung setempat.
SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL: